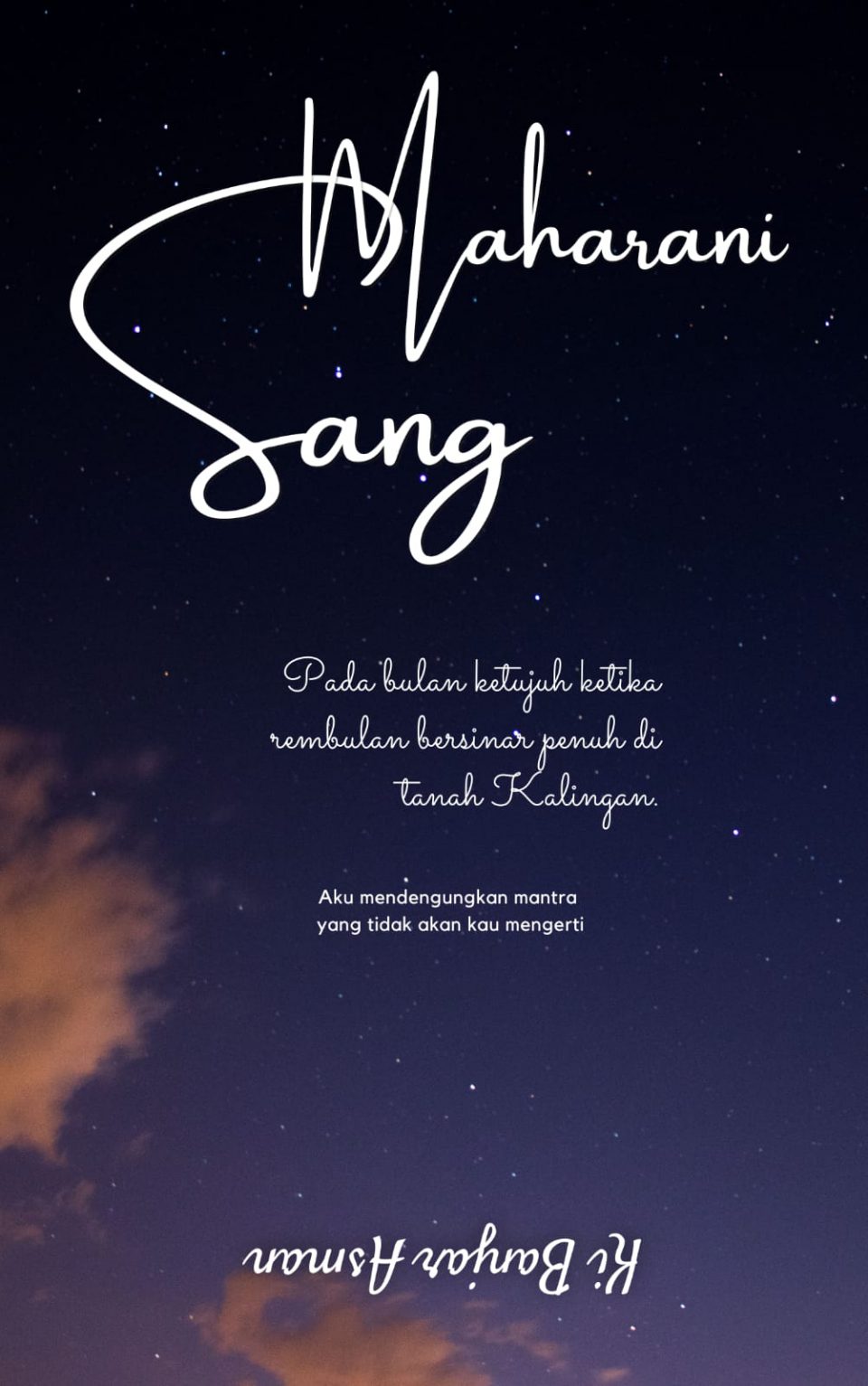“Sang Hyang,” ucap seorang pelayan ketika aku telah berada di sisi tempat berendam. Aku memandangnya sekilas dengan selarik senyum sebagai ungkapan terima kasih. Sepatutnya aku hargai mereka yang menungguku dengan tubuh membeku. Kesetiaan? Apakah mereka terus menerus memandangku ketika berada di kolam sempit itu? Apa yang mereka pikirkan tentang diriku? Mungkinkah mereka iri dengan kemolekan dan kulitku yang terang? Atau mungkin mereka ingin menyentuh payudaraku yang tak begitu besar? Tidak sepantasnya aku berpikir buruk mengenai prasangka mereka, terlebih mereka tidak membuka isi pikirannya padaku.
“Sang Hyang,” kara seorang lagi sambil memintaku merentangkan tangan dan kaki dalam keadaan telanjang. Ya, aku tidak terlapisi oleh benang atau kain tetapi aku patuhi permintaannya.
Tiba-tiba segumpal darah meluncur dari selangkanganku. Hitam, kenyal dan menebar anyir!
Pandanganku terpaku. Entah berkedip atau tidak, aku tidak tahu. Apakah dua pelayanku juga terkejut lalu bergerak atau membeku? Aku pun tak tahu.
Aku membungkuk untuk mengambil lalu memegangnya. Benar-benar terasa kenyal. Tanpa jijik, aku mengulurkannya pada seorang pelayanku sambil bertanya, “Apakah ini segumpal darah?”
Ia mengangguk. Ia merasa ngeri karena menjauh selangkah. Ia takut karena wajahnya pucat. Bibirnya bergetar karena takut.
Aku mengendus darah kenyal. Anyir. Amis. Aku mengembangkan telapak tangan agar puas mengamati benda aneh itu.
Yang aku lihat adalah seluruh kegelapan berada di dalam benda itu. Kepahitan dan kegetiran terangkum indah pada setiap bagiannya. Terlihat pula sayap-sayap yang terluka dalam penjara yang berbentuk benda lunak dan kenyal itu. Jauh di dalam gumpalan, aku dapat melihat seekor burung merak memandangku dengan ekor terkulai. Ia melihatku dengan kepala yang tak mampu menegakkan wajah. Aku ingin bertanya padanya tetapi jarak serasa membentang jauh, padahal sang merak berada di atas telapak tanganku. Mungkinkah aku tak mampu karena pikiranku yang terpenjara oleh belenggu prasangka?
Sekali lagi aku menjenguk kedalaman isi benda kenyal itu, namun yang ada hanyalah sehamparan padang tandus. Tidak ada rumput yang hijau melambai padaku. Tak juga ada sebatang pohon berdahan hijau yang membuka tangan untukku. Tidak ada. Nihil dalam pandang!
“Sang Hyang,” suara itu terucap dengan bibir bergetar. Tersendat dan aku mendengarnya dalam gelayut rasa pilu. Aku berpaling lalu melihat pelayanku telah menguasai diri. Ia memintaku untuk kembali merentangkan kaki dan tangan. Ia membungkus gumpalan darah hitam dengan kain berwarna merah yang lebih kecil dari sapu tanganku.
Baik, aku turuti permintaan pelayanku.
Kurang dari waktu selarutan kapur sirih, tubuhku telah disemati pakaian sederhana.
“Sang Hyang begitu anggun dan bersinar,” puji pelayanku dengan kepala mengangguk dalam.
“Benarkah?”
Keduanya mengembangkan senyum lalu mengangguk dalam.
“Tak seperti biasanya.”
“Sang Hyang benar-benar memancarkan perubahan nyata.”
“Aku tidak mengerti maksudmu.”
“Kami melihat Sang Hyang dalam wujud yang sempurna. Begitu indah.”
“Dapatkah kau beri gambaran untukku?”
“Bila kita melihat bulan terang, sepercik hitam selalu ada di bagian yang kita lihat. Bukankah Sang Hyang mengerti bahwa bulan tak pernah terlihat benderang dengan sempurna?”
“Ya. Ia tidak seperti matahari.”
“Begitu pula keadaan Sang Hyang pada pagi ini. Kami tidak mendapatkan gelisah pada wajah Sang Hyang. Tak ada pula semburat muram memancar dari pandang mata Sang Hyang. Di mata kami, Sang Hyang tampak lebih benderang dari bulan telanjang.”
“Semoga tidak ada orang bicara buruk untuk bulan telanjang.”
Aku pejamkan mata ketika dua pelayan mulai mengenakan pakaian untukku. Untaian peristiwa-peristwa yang tidak aku mengerti terus menerus tersembul dalam benakku. Aku menyaksikan ribuan penunggang kuda, ribuan senjata berayun mengerikan, kadang kala tampak sekelebat benda yang menyilaukan mata menyeberangi pelupuk mataku. Tak jarang aku melihat ribuan orang tersenyum. Sungguh, aku tidak mengerti.
Apakah itu semua adalah bayangan atau lukisan dari Mahadewa yang mungkin segera terjadi? Ataukah aku berada di dalam lukisan-lukisan itu di masa lalu? Sekali lagi, aku tidak mengerti. Namun aku sadar bahwa tidak semua yang terlihat oleh pandang hatiku dapat diungkap secara terbuka.
“Sang Hyang dapat mematut diri sekarang,” kata pelayanku dengan tiba-tiba.
Aku tersentak. Merah menjalar ruas wajahku, tetapi itu sekejap saja karena aku dapat menguasai diri.
Serangkaian kesibukan menanti dan aku terlibat di dalamnya.
“Dyah Murti,” lirih suara ibu menjalari ruang lebar hingga masuk ke dalam sentong. Aku tengah berada di sana. Menyendiri untuk terakhir kali di rumah ini.
Aku sedang dituntun oleh wibawa yang menggaung dalam jiwaku ketika ibu menyerukan namaku. Aku menggerakkan bibir dengan gemetar tanpa suara yang keluar. Aku tidak memahami sebab hilangnya suaraku, tetapi aku tidak peduli.
Aku tengah dirundung oleh kekuatan luar biasa yang membuat kesadaranku menguap untuk sesaat.