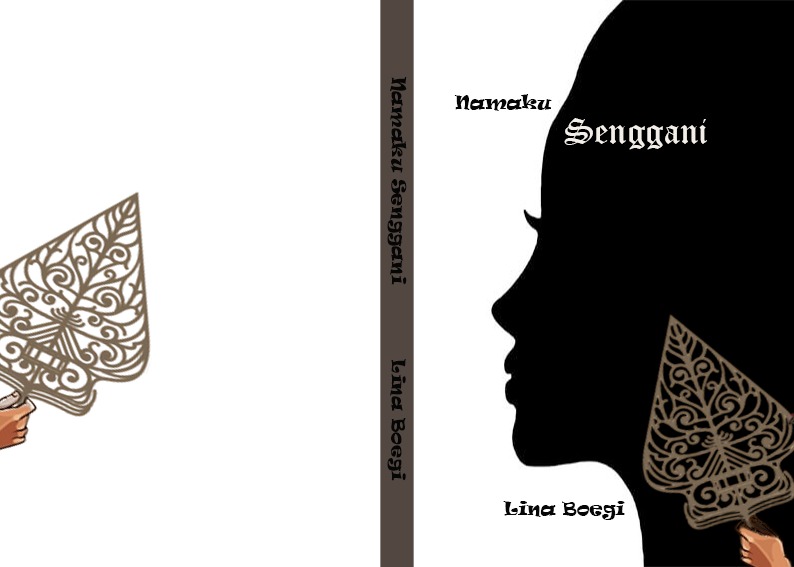Pada kuntum melati yang tumbuh di bawah jendela kamar, aku bertanya. “Bagaimana dengan diriku? Perempuan-perempuan itu terluka setelah dicampakkan, tapi aku menyemai luka dalam ladang rasa yang aku pendam dalam-dalam.”
“Kau yang memilih jalanmu sendiri, Senggani. Jalan terjal berduri yang kau tapaki dengan sepenuh hati.” Melati menjawab tanyaku dengan pandang mata mengejek.
“Cinta adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Datang dan menghuni hati tanpa diminta. Aku, kamu, dan siapa saja tidak sanggup memintanya datang atau pun menyuruhnya pergi.” Aku berusaha membela diri.
Melati tertawa dengan nada sumbang. “Jangan bicara hanya untuk membela diri, memenangkan inginmu sendiri. Cinta itu indah, Senggani. Cinta tidak melukai dan cinta sejati itu aanggup menyembuhkan luka dengan caranya sendiri.”
“Kau benar, cinta itu juga yang akan menyembuhkan sakit yang aku derita. Membalut luka-luka di sekujur tubuhku dengan keindahan dan kelembutan.”
Melati terbahak-bahak. “Kau lucu sekali, Senggani. Tidakkah kau sadari hatimu tengah tersesat? Hanya engkaulah yang mampu menemukan jalan untuk kembali, bukan Rendra atau siapa pun. Bawa hatimu kembali pada kebeningan, kasihani dia Senggani.”
Aku tergugu. Sebelah hatiku memihak pada melati, namun sebelah lainnya tegas menolak. Kukuh mencengkeram bunga cinta yang sedang mekar. Senyum Rendra membayang, aroma bunga cinta semerbak membuai rasa. Aku terlena.
Maka ketika laki-laki bermata cokelat itu menawarkan musim bunga kepadaku, tidak ada yang bisa aku lakukan selain tertunduk malu. Bersorak girang meski dalam hati, persis anak kecil yang mendapatkan hadiah. Sesuatu yang dia inginkan dan impikan menjelma sebuah kenyataan.
Aku melihat mendung di langit semakin kelam. Titik air yang mulai jatuh dari langit, terbawa hembus angin membasahi wajahku. Hatiku juga basah oleh luapan rasa yang buncahnya nyaris tidak sanggup aku bendung. Ini kah yang dinamakan bahagia? Ketika tangis, luka, dan kesedihan berlabuh di muara cinta. Tidak ada perih tersisa, hanya tawa dan sukacita.
Rinai hujan semakin keras menampar kaca jendela, hembus angin seolah mengajakku bicara.
“Hei, apa katanya tadi, kamu yang terbaik?” tanya angin mengusik bahagiaku. Aku yang tengah melayang tinggi ke angkasa, enggan untuk kembali ke bumi dan mencerna kenyataan yang ada. Ya, rupanya aku melupakan satu kenyataan jika yang terbaik itu sesungguhnya dapat memiliki banyak makna.
“Bisa jadi karena kau selalu ada untuknya, kau relakan telingamu menjadi pendengar setia, kau percaya padanya tanpa curiga, kau mudah dibodohi olehnya. Jangan terlena, Senggani. Terlalu besar pengorbananmu untuk sesuatu yang tidak lebih berharga dari apa yang sudah kau miliki sekarang.”
Celoteh angin memasuki telinga sebelah kanan kemudian keluar melalui telinga kiri. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersama Rendra. Menikmati hari bersama, merenda mimpi berdua. Itulah mimpiku yang sekarang menjadi nyata. Aku tidak mungkin melepasnya. Aku pasti memperjuangkannya.
Betapa aku selalu mengenang saat-saat membahagiakan itu. Saat aku begitu ingin meneriakkan kata mau, tapi rasa malu membuat lidahku kelu. Saat tubuhku terasa begitu ringan melayang menembus awan biru. Saat Rendra menatapku yang serta merta sibuk meredakan degup jantungku dan sekuat tenaga menyembunyikan rona di pipiku.
“Sepertinya kita butuh minuman hangat, tanganmu dingin sekali, Ani,” ucap Rendra membuat pipiku semakin merona.
Aku kembali mengeluh dalam hati, “Duh Rendra, aku tidak tahu harus ngomong apa. Seandainya aku bisa lebih terbuka seperti Lila, yang selalu tanpa beban mengungkap perasaannya. Bukan hanya malu, malu, dan malu.”
Bayangan Lila sahabatku yang blak-blakan itu berkelebat sekilas. Lila yang terbiasa ceplas-ceplos dan tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Lila yang rela berjuang mati-matian demi rasa cintanya untuk Ardy. Tidak sepertiku!
“Senggani sayang, berkenankah menerima ajakanki untuk minum teh berdua. Aku sungguh khawatir jari-jarimu akan membeku dan detak jantungmu kian memburu. Tidak baik untuk kesehatanmu, Sayangku.”
Jemariku mendaratkan satu cubitan di pinggang Rendra. Cubitan yang berhasil mengusir kedunguanku, cubitan yang mencairkan suasana. Selewat waktu berselang, kami sudah membaur dalam hiruk pikuk Surabaya. Membelah jalanan yang basah, lalu berhenti di warung bakso langganan. Menikmati semangkok mie bakso dan secangkir teh panas, sementara di luar rinai hujan semakin hingar.