Sabuk Utara
Apakah waktu dapat disebut sebagai siang? Atau sore? Apakah puncak tebing dan lereng sedang mendekap cahaya matahari? Entahlah, ukuran waktu di sisi utara tidak pernah terasa benar-benar hadir.
Kabut turun dari atas lereng seperti tirai yang ditarik perlahan. Mendung menekan langit, sekali-kali kilat membelah angkasa. Hujan jatuh dengan irama tetap.
Empat orang utusan Agung Sedayu menyusur jalan yang makin menyempit – lebih menyerupai jalur binatang daripada lintasan manusia. Tanah yang semula padat kini lunak; setiap langkah meninggalkan jejak yang segera dipenuhi air.
Mereka bergerak tidak pada barisan lurus. Perubahan kedudukan terjadi dalam barisan. Sukra berjalan di depan Pandan Wangi, berikutnya adalah Kinasih lalu Sayoga. Mereka semua membatasi pandangan – hanya membaca permukaan tanah beberapa langkah ke depan, samping kiri dan kanan, kecuali Sayoga yang sekali-kali menoleh ke belakang demi memantau pergerakan lima pasukan khusus agar tetap menyatu di belakang—hadir tanpa menuntut perhatian.
Tidak ada percakapan. Yang terdengar hanya gesek alas kaki pada lumpur, bunyi air yang tertekan akar, dan hujan yang memukul daun. Kabut membuat jarak menjadi pendek. Dunia seolah hanya seluas bentangan tangan saja.
Saat mereka tiba di kaki lereng, pergerakan berhenti sejenak. Pandan Wangi membagi tugas. Lima pasukan khusus segera menyebar, menempati titik-titik pemantauan untuk mempersempit ruang bidikan. Lima orang ini menyatukan tubuh masing-masing dengan keadaan alam yang tidak ramah. Ada yang merendahkan tubuh di balik semak basah, ada yang menempel pada permukaan tanah, ada yang menghadap jalur kedatangan mereka, ada pula yang menutup jalan mundur. Mereka tidak tampak, tapi batas terluar telah ditetapkan Pandan Wangi. Tidak ada yang akan melewati tanpa disadari.
Pandan Wangi mengamati singkat, membuat penilaian, menimbang jarak. Cukup.
Selanjutnya, mereka bergerak menuju punggung gunung. Jalanan licin, tanah bercampur batu kecil. Mereka tidak memanjat sekaligus. Satu naik, yang lain menunggu. Di depan adalah hutan yang mungkin ada jalan setapak, tapi mungkin juga tidak.
Kabut belum berhenti bergerak. Cahaya makin tipis. Dalam kesenyapan yang dibangun oleh alam, mereka berempat melangkah maju tanpa satu kata pun terucap.
Medan Timur
Dari jalur selatan, bende Menoreh dipukul.
Berdentang tidak nyaring. Hujan mencampuri gaung bende, kabut memecah jalur suara tapi getarannya mampu menjangkau dada, bukan telinga.
Kabut mengapung setinggi dada orang dewasa. Dia tidak datang sebagai tirai penghias pemandangan, tapi pembatas tegas antara hidup dan mati. Hidup terasa hanya berjarak sepuluh langkah di depan. Pekat, sesak dan terasa seperti dunia lain saat napas bercampur dengan uap air yang mengambang.
Senja seperti meninggalkan dunia lalu menghilangkan bekas agar tidak ada kesan pernah benar-benar hadir. Gelap menghunjam terlalu cepat ketika mendung tumpang tindah dan penuh sesak di angkasa.
Di bawah perintah Ki Demang Brumbung, pasukan Menoreh bergerak tenang. Mereka menyatu dengan tanah basah, merambat maju.
Lereng medan timur memberi perlindungan melalui permukaan yang tidak rata. Lumpur terbentuk di cekungan-cekungan rendah, pasukan Menoreh merayap mengikuti kehendak tanah yang tidak rata. Tidak perlu melangkahkan kaki karena cekungan adalah jebakan bagi pijakan yang menyimpang.
Dari balik jajar pohon kelapa bercampur dengan pohon lainnya, dari balik lipatan tanah yang tidak rata, pasukan Raden Atmandaru berada dalam diam yang serupa. Ki Sambak Kaliangkrik membiarkan hujan dan kabut yang bekerja untuknya. Dalam keadaan seperti ini, mengamati mangsa menjadi satu-satunya jalan yang tersedia.
Tak ada teriakan. Tak ada sorak. Yang ada hanyalah hujan, lumpur, dan bunyi bende yang perlahan mati di udara basah—meninggalkan ruang kosong yang penuh tekanan.
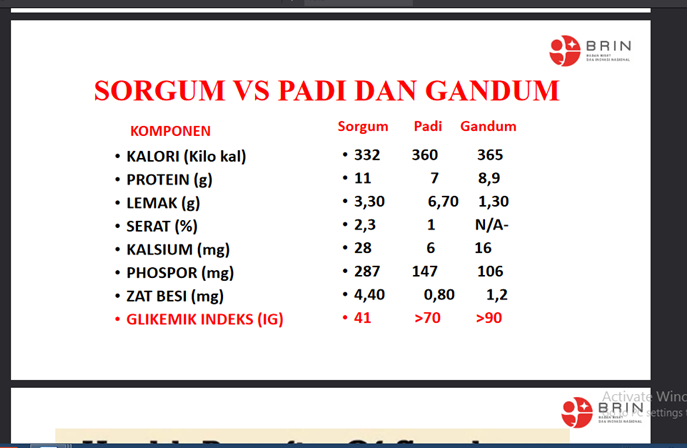
Lereng Barat
Dari jalur selatan, bende Menoreh dipukul.
Lereng yang bergelombang memberi mereka irama: turun, datar, turun lagi. Di cekungan, air menggenang sesaat lalu mengalir tipis; di punggungan kecil.
Kabut membatasi pandangan.
Glagah Putih berada di depan, jarak pandang sekepal tangan. Murid Ki Jayaraga ini membaca tanah melalui getaran yang merambat sampai telapak. Dia memperkirakan kedudukan lawan melalui perubahan bunyi air di bawah hujan.
Tanda digerakkan, pasukan Glagah Putih merayap tanpa aba-aba suara. Sesudah dentang bende hilang ditelan kekejaman alam, mereka luruh, menyamakan kedudukan dengan tanah, menyatu dengan lumpur melintasi semak basah. Merayap, tiap jengkal diambil dengan dada menekan bumi, siku mengiris genangan, lutut mencari pijakan di sela akar.
Mereka mencapai batas luar perkemahan tanpa melihatnya. Yang lebih dulu terasa adalah sungai kecil—parit alami—alur air sempit yang memotong lereng, berliku dan dangkal.
Glagah Putih menghentikan pasukannya. Ada yang tidak beres di tubuh parit, pikirnya. Dia meratakan telapak tangannya sekali lagi. Getaran memantulkan kekuatan yang memang berbeda. Bukan dinding atau batu yang ditanam. Glagah Putih maju sendirian, memasukkan setengah tubuh ke dalam aliran, tangannya menjangkau bagian depan.
Bambu runcing yang ditanam dengan ujung yang sama tinggi dengan permukaan air yang mengaliri parit!
Senjata rahasia yang mematikan!
Glagah Putih beringsut mundur. Mengatakan sesuatu pada anak buahnya dengan gerakkan tangan. Mereka mengerti. Pasukan menyeberangi parit, merayap sejengkal demi sejengkal perlahan, lalu tiarap di bibir parit yang terlindung semak.
Di sana mereka berhenti.
Tubuh disusun sejajar alur, kepala rendah, mata awas menatap arah perkemahan. Dari balik kabut, perkemahan hadir sebagai bayangan. Tidak ada perintah lanjutan.
Glagah Putih menunggu satu bunyi yang lain. Parit bukan lagi halangan dan bukan pula menjadi batas.
Jalur Selatan.
Dari jalur ini, bende pihak Mataram dipukul kuat-kuat. Bunyi logamnya tidak lantang, memantul pada dinding parit lembek, menyebar sebagai getaran, bukan suara yang dilantangkan.
Jalur selatan menjadi medan yang berbeda dengan lembah biasa: parit mendadak penuh alami dengan genangan air; parit terjalin dengan cabang-cabang aliran sungai purba—lekuk-lekuk tua yang kini menjadi lorong gelap berlumut. Semak dan tanaman perdu tumbuh liar, basah, menutup pandang hingga jarak tinggal beberapa tombak.
Ki Prana Aji mengangkat tangan setinggi dada—isyarat senyap. Pasukannya merayap, tiarap, memanfaatkan parit purba sebagai pelindung. Napas tidak dibuang begitu saja; kain melekat pada kulit; lumpur menelan telapak. Setiap gerak disesuaikan denyut hujan.
Ki Garu Wesi mengawasi medan melalui pantulan suara: getar bende yang merayap dari bentangan tanah di depannya.
Perkemahan Raden Atmandaru.
Bunyi bende dari selatan tidak mengejutkan kelompok Raden Atmandaru.
Pasukan mereka tetap tenang pada kedudukan masing-masing sambil sekali-kali memandang arah pemimpin regu.
Nyala oncor tampak kepayahan menembus kabut yang memangkas jangkauan cahaya. Kegiatan di dalam perkemahan seperti tidak ada sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Perkemahan nyaris sunyi sama sekali. Api unggun dipadamkan. Hanya bara tertutup abu yang masih menyimpan panas. Sebagian orang memanfaatkan waktu untuk istirahat, tapi ada pula yang berjaga di balik batas luar perkemahan.
Ki Sonokeling menggeser kakinya perlahan. Kayu gelap itu basah, licin, dan dingin. Dia menutup mata sejenak, mengukur jeda setelah bunyi bende. Tidak ada teriakan lanjutan, tidak ada derap kaki. Kabut terlalu rapat untuk gerakan kasar. “Jalur selatan,” katanya akhirnya. “Tapi suara tidak datang persis dari depan perkemahan.”
Raden Atmandaru mengangguk. Pikirannya bercabang; mungkinkah Sedayu datang dari utara atau justru sedang menunggunya di sana?
Ki Sonokeling memandang sekeliling yang sebenarnya sudah penuh dengan kabut. “Malam ini, apa yang dapat mereka kerjakan di luar perkemahan?” Dia bertanya pada dirinya sendiri membuat perkiraan yang paling mungkin direncanakan Agung Sedayu. Api harus diabaikan karena sulit untuk menyala. Menyerang perkemahan secara langsung dari segala jurusan? Itu menghabiskan terlalu banyak tenaga dan cukup berbahaya karena jarak pandang sangat terbatas. Kawan dan lawan sama-sama tidak terpantau penglihatan.
Raden Atmandaru melihat gerak gerik Ki Sonokeling yang sepertinya sedang gelisah. “Apakah Kyai dapat meraba kemungkinan yang terjadi berikutnya?”
Ki Sonokeling menggeleng, ucapnya, “Tidak mudah bergerak dalam keadaan seperti sekarang ini. Tanah berlumpur, kabut pun tidak menyisakan jarak pandang..” Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi setelah menarik napas panjang, “Yang pasti sangat sulit jika menggerakkan pasukan karena keterpaksaan. Seandainya Sedayu ingin merebut kemenangan, lalu memaksa pasukannya maju menyerang, saya pikir itu benar-benar keputusan paling bodoh yang pernah dibuat seorang panglima. Jadi, pada titik ini, saya kira Sedayu pun akan mengundurkan waktu sampai fajar.”
“Jika kita ikut dalam diam, maka biarkan mereka mengira kita terpaku di dalam perkemahan,” kata Raden Atmandaru.
“Apakah Raden tetap akan menunggu Sedayu seandainya besok masih belum ada gerakan?” tanya Ki Sonokeling.
Raden Atmandaru bangkit berdiri dengan hela napas panjang yang halus. “Pengandaian menjadi kata yang sebetulnya harus mulai dilarang, Kyai. Kita tidak mendapat waktu untuk berandai-andai.”
“Mengerti,” sahut Ki Sonokeling.


