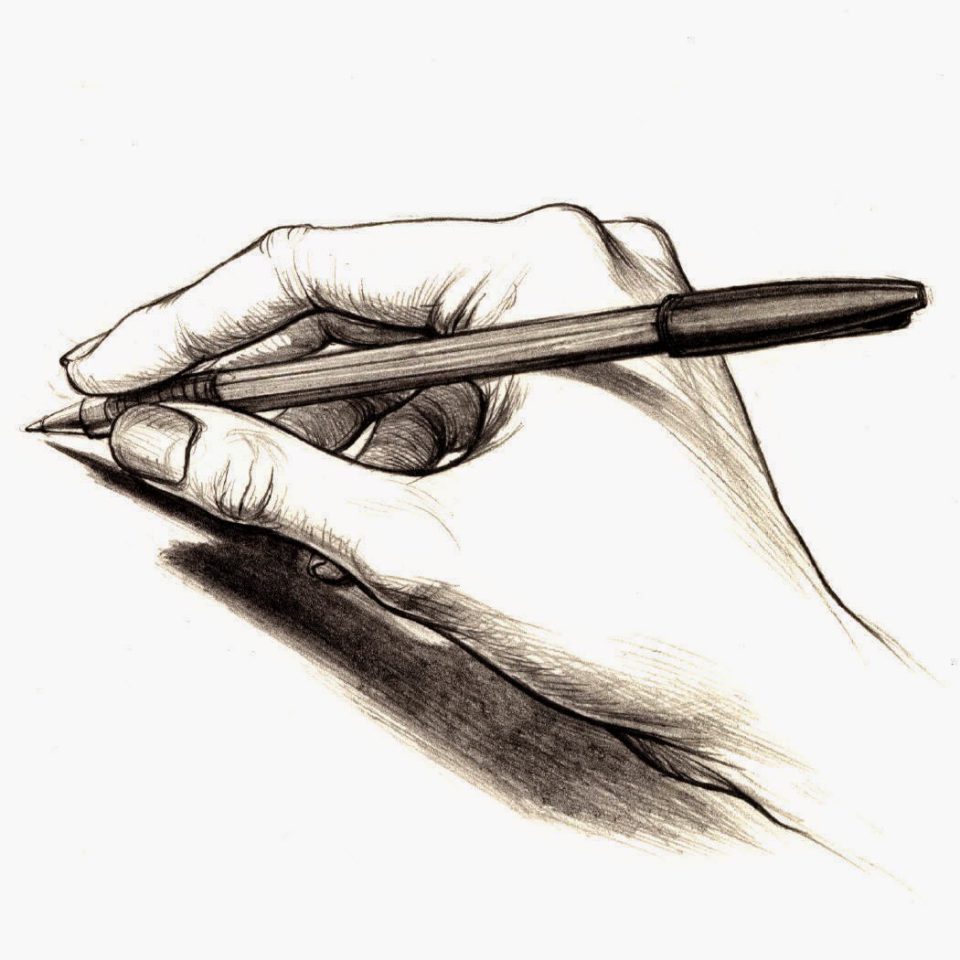Cak Heru Prabowo
Overture: Orkestra Nubuat yang Menggelegar
Panggung sejarah terbuka dengan dentuman gong gamelan, menyusul derap timpani dan lengking trompet. Dari kabut fajar, dua sosok hadir dalam panggung imajinasi: Prabu Joyoboyo, raja Kediri yang menembang nubuat puitis, dan Nostradamus, tabib sekaligus peramal dari Provence yang menuliskan kuatrain penuh teka-teki. Mereka tak pernah bersua, tetapi di ruang kesadaran Nusantara hari ini, suara mereka bergema bersama, membentuk gending kosmik.
Joyoboyo menembang dalam Jangka Jayabaya:
> “Yen wus ana kreta tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prahu mlaku ing dhuwur awang-awang, iku tandha yen jaman edan wis cedhak.”
(Apabila ada kereta tanpa kuda, Jawa dililit besi, perahu berlayar di atas awan, itu tanda zaman edan telah dekat.)
Bait itu seperti gong besar: menyindir moralitas yang rapuh di tengah kecanggihan teknologi. Jalan raya dipenuhi mobil tanpa kuda, langit dilintasi pesawat, dan kota-kota kita terkepung baja — tanda zaman edan yang tak lagi sekadar nubuat.
Nostradamus menjawab lewat Les Prophéties, Century I, Quatrain 35:
> “Le lion jeune le vieux surmontera, / En champ bellique par singulier duel…”
(Singa muda akan mengalahkan yang tua, di medan perang dalam duel tunggal…)
Baitnya bagai gesekan biola minor — samar, misterius, namun menggetarkan. Tafsirnya tak pernah usai: dari perang suksesi, konflik kekaisaran, hingga rivalitas geopolitik masa kini.
Nubuat keduanya bukan peta pasti, melainkan protes estetis. Ia adalah sindiran, kegelisahan yang dibungkus simbol. Nubuat adalah gamelan batin: tak memberi jawaban, tapi menggetarkan kesadaran. Pertanyaannya — apa arti nubuat itu bagi Nusantara hari ini, yang berdiri di pusaran globalisasi, krisis ekologis, dan ledakan teknologi?
Andante: Jahitan Makna & Konsep
Tempo melambat. Panggung kini diterangi cahaya redup, seakan sebuah pendhapa tempat para guru peradaban duduk berembug. Dari dunia Islam dan humaniora, hadir Ibn Khaldun, Al-Farabi, Malik Bennabi, dan Syed Naquib al-Attas. Mereka menafsir nubuat dengan akal budi, menjahit benang mistik menjadi kain pemikiran.
Ibn Khaldun: Siklus dan Asabiyyah
Dalam Muqaddimah, ia menulis:
> “Ilmu sejarah adalah berita tentang masyarakat, peradaban, perubahan bangsa-bangsa, dan sebab-sebab pergeseran itu.”
Bagi Khaldun, nubuat adalah cermin hukum sejarah. Peradaban lahir dari asabiyyah (kohesi sosial), tumbuh dengan solidaritas, dan runtuh ketika egoisme merajalela. Nusantara kini menghadapi ujian besar: polarisasi politik yang memuncak sejak Pemilu 2019 hingga 2024, di mana propaganda media sosial dan pasukan siber memperburuk perpecahan identitas, menyisakan luka sosial yang belum sembuh sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah asabiyyah bangsa ini masih cukup kuat untuk menopang kejayaan?
Al-Farabi: Kota Fadilah
Dalam Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah, ia menulis:
> “Tujuan tertinggi manusia adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hanya tercapai dalam masyarakat utama, di bawah pimpinan seorang utama.”
Nubuat Joyoboyo dan Nostradamus bisa dibaca sebagai alegori pencarian pemimpin fadilah (bijaksana). Nusantara modern penuh hiruk-pikuk politik elektoral, tapi apakah kita tengah menuju kota fadilah atau hanya kota gaduh?
Malik Bennabi: Energi Ide
Dalam Les Conditions de la Renaissance, Bennabi menulis:
> “Masalah kita bukan kekurangan materi, melainkan kemandulan ide. Peradaban lahir ketika manusia, tanah, dan waktu dipersatukan oleh ide penggerak.”
Nubuat menggugah imajinasi, tetapi tanpa ide produktif ia hanyalah bayangan. Indonesia penuh bonus demografi dan sumber daya, namun disrupsi kecerdasan buatan menuntut talenta digital hingga sembilan juta orang pada 2030. Bennabi mengingatkan, yang kita butuhkan bukan sekadar nubuat, tapi energi gagasan untuk menavigasi disrupsi ini.
Syed Naquib al-Attas: Krisis Adab
Dalam Islam and Secularism, ia menegaskan:
> “Krisis utama umat Islam adalah krisis adab. Bila adab hilang, maka ilmu tidak lagi pada tempatnya, dan manusia kehilangan kemanusiaannya.”
Nubuat adalah teguran atas hilangnya adab: ilmu yang diperalat untuk hoaks, teknologi dipakai menipu, kekuasaan tanpa martabat. Adab adalah saron gamelan: mengatur harmoni agar tidak fals. Tanpa adab, nubuat hanya tinggal gema, dan peradaban pun runtuh dari dalam.
Finale: Allegro Nusantara
Tempo kini meningkat. Kendang bertalu, gong ageng menggema. Semua suara—Joyoboyo, Nostradamus, Khaldun, Farabi, Bennabi, al-Attas — berbaur dalam gending nusantara.
Nusantara berdiri di persimpangan. Globalisasi membawa peluang sekaligus ancaman; teknologi mempercepat segalanya, tetapi juga menciptakan jurang. Krisis iklim, krisis sosial, dan krisis adab menyelimuti zaman edan kita. Namun, peluang itu tetap ada.
Bila asabiyyah dinyalakan kembali lewat solidaritas sosial,
Bila kota fadilah dibangun melalui tata kelola bijak,
Bila ide-ide segar ditanam dan diberi pupuk,
Bila adab ditegakkan sebagai fondasi,
maka nubuat tidak lagi sekadar gema kosmik. Ia menjelma inspirasi praksis, peta batin yang mendorong tindakan nyata.
Penutup
Simfoni ini mengalir dari dentuman nubuat hingga renungan akal budi, lalu menuju harapan bagi Nusantara. Seperti sebuah gending, ia penuh lapisan makna: dari gong yang menggelegar hingga kendang yang menuntun tarian. Ia mengajak kita menari dalam kesadaran—menjahit masa lalu, menimbang masa kini, dan menulis masa depan.
Glosarium
Jangka Jayabaya: Kitab ramalan yang dikaitkan dengan Prabu Joyoboyo, raja Kediri abad ke-12.
Les Prophéties: Kumpulan ramalan Nostradamus dalam bentuk puisi empat baris (kuatrain).
Asabiyyah: Konsep Ibn Khaldun tentang solidaritas sosial atau kohesi kelompok.
Kota Fadilah: Konsep Al-Farabi tentang masyarakat utama yang dipimpin oleh pemimpin bijak.
Adab: Tata nilai, etika, dan martabat manusia menurut tradisi Islam.
Gending: Komposisi musik gamelan Jawa.
Nubuat: Ramalan atau pesan simbolis tentang masa depan, sering kali bersifat metaforis, bukan prediksi literal.
Teropong Pustaka
Ibn Khaldun, Muqaddimah (1377, Arab). Membaca sejarah sebagai ilmu sosial yang menjelaskan pola lahir–runtuh peradaban; relevan untuk memahami dinamika bangsa. Terjemahan Inggris oleh Franz Rosenthal (1958).
Al-Farabi, Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah (940, Arab). Menawarkan visi masyarakat beradab, sangat penting untuk merefleksikan kualitas kepemimpinan di era modern. Terjemahan Inggris oleh Richard Walzer (1985).
Malik Bennabi, Les Conditions de la Renaissance (1948, Prancis). Menegaskan bahwa ide adalah bahan bakar utama peradaban; inspiratif bagi Indonesia yang sedang mencari arah baru.
Syed Naquib al-Attas, Islam and Secularism (1978, Inggris). Mengingatkan bahaya hilangnya adab dalam dunia modern, relevan dengan problem krisis moral dan intelektual kini.
Clifford Geertz, Negara Teater: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980, Inggris). Sebuah etnografi yang menggambarkan simbol dan kekuasaan di Jawa dan Bali, memberi lensa tambahan untuk memahami nubuat Joyoboyo dalam konteks budaya.
Surabaya, 17 08 25.