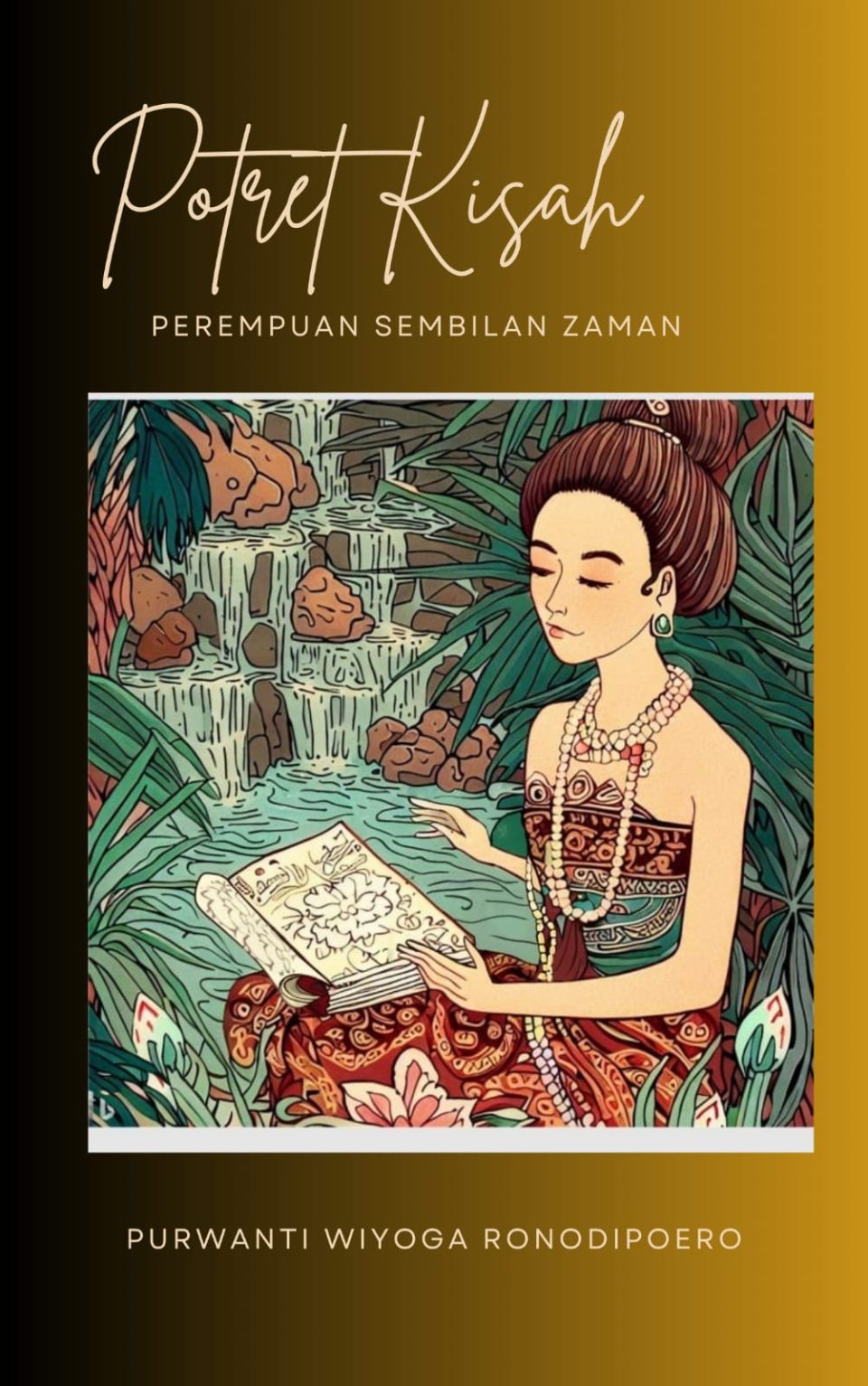Aku tidak melihat kesibukan berkemas pada keluarga kami. Baik ibu maupun bapak tidak menyuruh kami untuk membungkus pakaian dan yang lainnya. Aku kira bapak memilih untuk bertahan. Kami tidak mempunyai jalan lain karena kakakku, yang berumur 14 tahun, terserang penyakit typhus. Itu adalah keadaan sulit yang mampu memaksa kami menjalani hidup di bawah tekanan yang cukup berat.
Saat clash atau benturan kedua itu berlangsung, aku masih berumur enam tahun. Sepanjang hari adalah waktuku untuk bermain. Bagian depan rumahku adalah tanah lapang. Rumahku dikelilingi jalan-jalan yang banyak tanjakan dan turunan. Berlari dan bergulingan menjadi salah satu kesukaanku waktu itu. Bermain pasar-pasaran menjadi salah satu kegiatan yang aku lakukan bersama saudara-saudaraku. Sepunggung gunung yang tegak menghadap bagian depan rumahku tampak begitu kokoh dan perkasa menjulang. Ketika langit bersih tidak berawan, gunung itu seakan-akan sedang bernaung di bawah atap yang berwarna biru. Begitu cantik dan indah. Pada waktu yang lain, aku dapat merasakan sejuknya angin yang bertiup menuruni lerengnya.
“Gunung Sindoro,” jawab salah seorang yang bekerja di rumahku ketika aku bertanya mengenai gunung itu.
Pekarangan dan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar rumahku adalah tempat singgah dan rumah bagi burung-burung. Aku kerap mendengar burung-burung berceloteh dan bernyanyi gembira seperti sedang menyongsong air yang turun dari langit. Aduhai, bila mengingatnya sekarang maka begitu terang bagiku bahwa masa kecil adalah masa segala sesuatu begitu indah dan sederhana.
Aku belum mengenal dan belum mengerti arti kata sedih atau takut, hingga tiba suatu hari sewaktu ada sebuah truk yang penuh dengan tentara Belanda berhenti di depan rumah.
Pada saat hari masih siang, ketika peristiwa yang sulit dilupakan itu berlangsung, serombongan orang berseragam dengan kepala berikat kain warna merah melompat turun dari prahoto atau truk. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai anjing NICA oleh orang-orang di sekitar kami. Aku tidak tahu alasan mereka disemati julukan anjing NICA. Sesaat kemudian, mereka sudah berjalan memasuki pekarangan, berderap dengan langkah sedikit cepat, mendatangi rumah kami. Wajah mereka sama sekali tidak memperlihatkan wajah yang ramah atau bersahabat. Seperti ada kilatan marah yang keluar dari sorot mata mereka. Aku hitung mungkin ada sekitar enam orang bersenjata laras panjang dengan sangkur yang terpasang pada ujung senapan. Mereka mendorong pintu dengan kasar, memaksa masuk lantas mengacungkan sangkur yang berkilat kepada kami. Mereka menyatakan ingin memeriksa kamar Mas Pur. Barangkali mereka ingin membuktikan kebenaran kabar yang mereka terima. Tubuhku bergetar, kulitku meremang ketika melihat wajah beringas orang-orang yang mengayun-ayun sangkur yang berkilauan seakan sedang mengancam keselamatan jiwa kami. Aku terperangkap dalam kengerian yang mencekam di dalam rumah.
Namun matahari di rumah kami masih tegar bersinar. Matahari itu adalah bapak yang menghadapi mereka dengan gagah berani. Bapak bertukar kata dengan mereka. Bapak bersoal jawab dengan pemimpin mereka, tapi aku tidak tahu yang sedang mereka percakapkan. Aku tidak tahu sedikit pun yang dikatakan bapak pada mereka. Beberapa waktu berlalu, ketakutanku mereda setelah mereka menurunkan sangkur lalu berbalik pergi meninggalkan kami. Selepas kepergian serdadu Belanda itu, ibu bergegas memasuki kamar Mas Pur Aku mengikuti ibu dari belakang lalu melihat beliau mengusap kening dan kepalanya.
Saat ini aku ingin katakan bahwa kami bukan keluarga terpandang yang memiliki segalanya. Bukan pula termasuk orang-orang yang mudah mewujudkan keinginan. Untuk beberapa waktu lamanya, ibu tidak terlihat memberikan obat dari dokter atau ramuan dari dukun pada kakakku. Aku dan dua kakak perempuanku lebih sering melihat ibu menjadikan cacing gelang sebagai obat penawar. Beliau mengambil cacing gelang dari bawah pohon pisang yang tumbuh di halaman kami. Cacing kemudian dipotong-potong, dibersihkan bagian dalamnya lalu dikukus. Air kukusan cacing pun menjadi obat yang harus diminum Mas Pur. Demamnya berangsur turun.
Keterangan : Anda dapat menjadikan kisah ini sebagai koleksi. Hubungi Ki Banjar Asman/WA