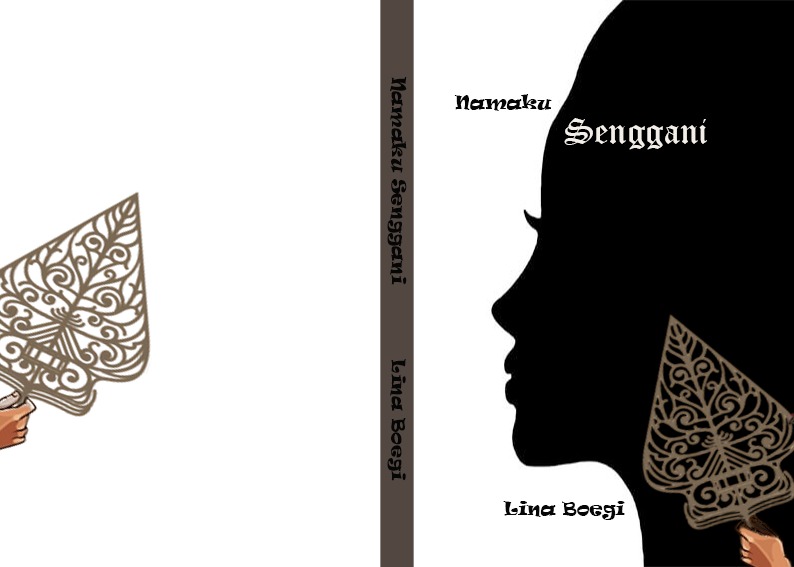Aku sedang menikmati makan malam bersama ibu di amben dapur. Rinduku mulai mencair dan membaur dalam citarasa nasi thiwul dan bothok layur. Urap kembang turi dan daun jeprok dari rumah simbok membuat lidahku riang mengecap rindu. Rindu yang telah terjawab, tuntas sudah.
“Makan yang banyak, Ani. Di kota ndak ada makanan kayak gini.” Ibu mengangsurkan cething berisi bothok layur.
Aku menggeleng. “Bapak sudah makan, Bu?”
“Sudah, Nduk. Bapak diundang kauman di rumah mbah Parto selepas ashar tadi.” Ibu menyodorkan sepiring urap, aku menggeleng.
“Cukup, Bu. Ani selalu ingat pesan mbah Kung. Makanlah secukupnya dan jangan berlebihan. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan.”
Ibu mesem lalu ngendikan, “Ibu lega, Nduk. Jebule kota tidak sepenuhnya mengubahmu.”
“Panjenengan sampun kuwatir, Ani memang tinggal di kota, tapi yang mengalir di tubuh ini adalah darah wong ndeso. Darah bapak dan ibu.” Kalimat manis meluncur dari bibirku.
Kami saling menatap. Bintang-bintang bertaburan dalam bola mata. Pendar keindahan nyata dalam kerlipnya, dalam segaris senyum yang mengembang di bibir kami.
Dari jendela dapur dapat aku tangkap pancaran lampu teplok memantulkan bayangan bapak yang tengah duduk di lincak. Aku jadi ingat kalau bapak menungguku.
“Lekaslah ke sana, Nduk. Cangkingen kopine bapak,” perintah ibu sambil membereskan sisa makan malam.
Terdengar suara lincak kemriyet saat aku hempaskan tubuh di samping bapak. Kami terpaku dalam dekap hening, mengembara dengan pikiran masing-masing. Sesekali terdengar decap lidah bapak saat menghirup kopi.
Nyala kunang-kunang bersitkan tanya dalam pikiran, “Mampukah aku seperti kunang-kunang yang tetap menyala dalam gelap dan memberi terang pada orang-orang yang tersesat?”
Tiba-tiba bayangan keris itu melintas. Bersinar dalam gelapnya ketidaktahuan. Berpijar dalam dingin ketidakacuhan. Ah, rupanya aku buta dan tuli selama ini. Tidak melihat dan tidak mendengar, juga tidak peduli.
Oh Gusti, nyuwun pangaksami.
Nyanyian belalang menerangi jalan pikiran. Padahal seringkali ibu ngendikan, “Ndak ada orang tua yang rela njlomprongne anake, Nduk.”
Namun baru sekarang aku menyadari. Jika selama ini wasiat mbah Kung dan permintaan bapak merupakan sebuah beban berat, semata-mata karena prasangka yang telah membutakan mata hatiku.
Bapak berdeham pelan, disusul sebuah tanya yang mengejutkan, “Apa yang kamu tahu tentang keris, Nduk?”
Lamunanku buyar, tapi tidak bersama penyesalan. Dia berbaring nyaman dalam salah satu ruang di hatiku. Sementara ingatan tentang masa lalu menyelimutiku erat.
Tergagap aku menjawab, “Sebatas yang sampun Bapak dhawuhaken.”
“Itu saja? Kamu ndak pengin tahu lebih banyak tentang keris?”
“Awalnya boten, Pak. Tapi sekarang saya punya pemikiran, bahwa mbah Kung pasti mempunyai sebuah tujuan. Jadi, saya putuskan bahwa saya harus belajar tentang keris.”