Laga Pecah di Kali Tinalah
Sepertinya hujan memang tidak pilih-pilih tempat atau golongan.
Air turun dengan kecepatan tetap di perkemahan Raden Atmandaru. Sunyi tapi beberapa orang tampak melakukan kegiatan di tanah terbuka.
Seorang petugas sandi melaporkan keadaan Tanah Perdikan yang lengang sejak pagi. ”Mungkin karena kematian Ki Gede dan hujan tak kunjung berhenti, sayakira begitu,” ucap petuas sandi menutup laporan ketika Raden Atmadnaru bertanya sebab yang memungkinkan.
Ki Sonokeling menarik napas halus. “Agung Sedayu tidak dapat dilepaskan. Watu Sumping adalah tanda yang terdekat dengan hari ini. Kita bisa melihat medan utara yang seperti sengaja dibuka, meskipun kita lolos, tapi itu bukan kemenangan yang dapat dibanggakan. Kecurigaanku adalah seolah Agung Sedayu sengaja memberi kita ruang.”
Raden Atmandaru mendengarkan tanpa memotong. Lengang itu berarti jalur terbuka, tapi juga berarti pengawasan dipusatkan di titik tertentu. “Semuanya masuk akal. Hujan, kabut dan lumpur. Medan utara pun juga dibuka karena pertimbangan wajar meskipun tidak utuh karena mereka juga menempatkan pasukan di sana. Saya kira ini bukan pembiaran tanpa pengawasan,” ujarnya. “Ada petugas sandi yang belum datang memberi laporan. Itu artinya ada satu ruang kosong berarti ada yang dijaga ketat.”
Ki Suta Jaladri tampak berpikir keras. Dia membuat guratan kasar di atas permukaan tanah. Orang-orang segera melihat ke bawah. “Kediaman Ki Gede dapat didekati dari banyak arah. Tapi seluruhnya mempunyai kemungkinan benturan terbuka. Mungkin tidak kalah jumlah maupun medan, tapi sepertinya terlalu mudah dilakukan.”
Raden Atmandaru mengangguk setuju. “Hari ini adalah hari mereka berduka. Mungkin sudah masuk pada hari kedua atau ketiga. Alam mewakilkan pada hujan demi mendukung kita semua. Saya pikir serangan senyap berasa ledak tinggi dan menghancurkan dapat dilakukan.”
Ki Sonokeling mengerutkan kening, lalu memandang Ki Suta Jaladri yang sudah bertahun-tahun tinggal membaur di Tanah Perdikan.
Namun Ki Suta Jaladri, meski tahu sedang menjadi pusat perhatian, malah seakan menunggu seseorang melepas kata-kata.
Pembicaraan menambah sedikit waktu sedangkan waktu sendiri enggan ditandai.
Raden Atmandaru mengirim satuan serbu dengan tujuan antara; Dusun Benda. Jalur yang tersedia cukup lebar, memungkinkan empat ekor kuda berjalan sejajar tanpa perlu saling mengalah. Permukaannya padat, bercampur kerikil halus yang menahan air hujan agar tidak menggenang.
Di kiri kanan jalan, semak rendah tumbuh tidak rapat. Pohon-pohon berdiri tak beraturan. Kabut menggantung rendah, tipis dan bergerak perlahan, tidak menutup jalan, hanya mengaburkan jarak.
Satuan serbu Raden Atmandaru tegak lurus, percaya pada barisan dan kecepatan.
Kedatangan mereka memang mengejutkan Ki Lurah Sora Sareh dan Ki Sulur. Jalur Dusun Benda bukanlah jalur terbaik bagi serangan yang melibatkan pasukan berkuda. Tapi keduanya sudah tidak mungkin berpikir lebih dalam dan lebih jauh!
Dari sisi tebing Kali Tilanah, serangan datang mendadak,
Para pemanah Tanah Perdikan menghantam barisan terdepan. Sebagian lolos, terus menerjang! Pasukan berkuda Ki Lurah Sora Sareh menyongsong di sudut sempit, sedikit lebih sudut tajam. Tombak dan senjata pendek menyusup di sela-sela benturan. Dua pasukan berkuda berbenturan, sebagian terpaksa berhenti tapi tidak untuk lari!
Dalam kekacauan itu, baik Ki Suta Jaladri maupun Ki Lurah Sora Sareh sudah memperlihatkan kelebihan masing-masing. Mereka menakar, mengatur gelar dan sepertinya dua orang ini memang seimbang.
Permukaan sungai yang dangkal tidak menjadi alasan bagi Kinasih melambatkan gerakan. Dia belum bergerak – sebatas melindungi atau mendukung penunggang kuda yang berada di dekatnya. Kinasih tidak melambat karena tahu bahwa dirinya berada di bawah perintah lurah pasukan khusus seperti di Watu Sumping. Dia hanya menunggu perintah Ki Sora Sareh.
Perintah dilantangkan untuknya!
Kinasih berkelebat, melesat, memanfaatkan dinding tebing, kepala kuda dan sebagainya sebagai alat panjat. Yah, Kinasih mendapatkan tugas berat; menghantam bagian tengah pasukan berkuda lawan, memutus aliran serangan.
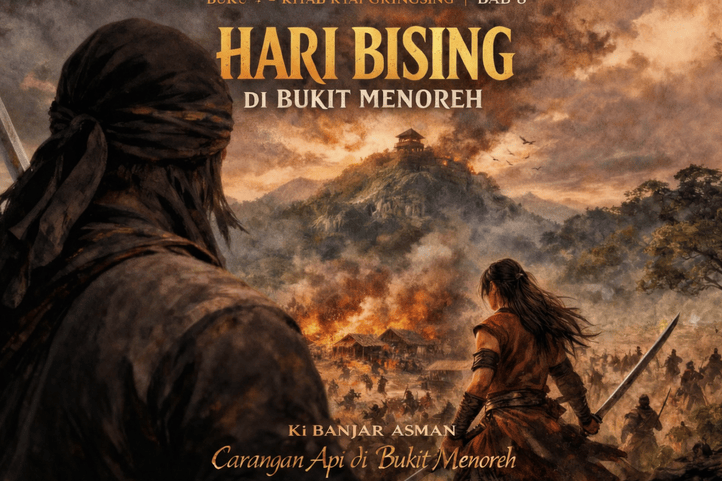
Hujan turun tanpa peduli waktu.
Di barak pasukan khusus, yang berdiri puluhan tombak di selatan pasar induk. Atap basah, halaman sepi, penjagaan rapat tanpa gerak berlebih. Ki Lurah Sanggabaya melaporkan keadaan sekitar. Pasar lengang lebih cepat dari biasanya. Jalur selatan bersih, jalur barat terlalu terbaca.
“Semua orang sudah menempati kedudukan sesuai rencana,” katanya.
Ki Prana Aji menimpali singkat, “Saya belum dapat memberi kabar perkembangan terkini, ada yang belum kembali.”
Mereka berdua memandang wajah Agung Sedayu yang menyimpan banyak makna. Tegang tapi dengan perhitungan. Dua anak buah Agung Sedayu itu sadar bahwa lawan yang sedang dihadapi sudah tentu tidak termasuk orang yang gegabah mengambil keputusan.
Suasana di barak pasukan khusus jauh berbeda dengan biasanya. Kematian Ki Gede dan larangan yang dijatuhkan pada Pandan Wangi seolah membuat segala sesuatu menjadi beku. Tidak ada gurau atau canda tawa ringan. Semuanya beredar dengan perhatian pada satu orang; Agung Sedayu.
Senapati Mataram yang membuat banyak orang terkejut dan terpukul dengan siasatnya itu lantas duduk. Dia mereka ulang medan utara, kediaman Ki Gede, sisi belakang kediaman dan jarak antarruang penjagaan.
Ki Lurah Sanggabaya mengangkat lagi soal mata-mata yang belum kembali.
Agung Sedayu kemudian berkata, “Kita bisa menunggu dan bisa juga tidak menunggu.” Lalu melangkah keluar ruangan. Menengadahkan wajah seakan sedang mencari penanda waktu, tapi semuanya sirna. Mendung masih tebal bergelantungan di langit Menoreh. Kemudian kembali masuk, katanya, “Kirimkan empat petugas.” Agung Sedayu merinci tugas untuk empat orang tersebut.
Ki Prana Aji, pemimpin medan utara yang runtuh itu, lantas keluar ruangan. Keheningan sudah menjadi pesan meskipun dia sudah kembali masuk. Dia saling bertukar pandang dengan Ki Lurah Sanggabaya tapi tidak ada kata-kata.
“Ki Rangga,” kata Ki Prana Aji kemudian, “apakah kita tidak menunggu bantuan dari Mataram?”
Agung Sedayu tidak lantas menjawab. Dia mengangguk lalu menarik napas datar. “Tanah ini tidak pernah meminta bantuan. Ki Gede tidak pernah mengajarkan hal demikian pada kami di masa lalu.” Pemimpin pasukan khusus itu menutup kalimatnya dengan diam yang panjang.
“Bantuan hanya berguna bila kita masih punya kebutuhan,” lanjutnya. Suaranya rendah, tidak menggurui. “Beberapa orang tidak memenuhi rencana. Itu bukan salah mereka atau siapa saja tapi masih bisa dijelaskan.”
Ki Prana Aji mengangguk dalam-dalam. Ada yang tertinggal berarti ada kendala yang sulit dilewati.
Tak lama kemudian, empat petugas sandi masuk tanpa suara, lalu pergi tanpa kata-kata. Pintu ditutup perlahan. Barak kembali sunyi, hanya jangkrik dan serangga malam lainnya yang tetap mampu bernapas panjang.
“Bagian utara bukan karena kawan-kawan kita gagal mencegah, tapi memang kemampuan mereka berada di atas rata-rata. Pertahanan terakhir di kediaman Ki Gede juga tidak dapat ditimpakan pada seseorang. Meski demikian, saya tidak ingin mengatakan kita kalah oleh keadaan. Bukan seperti itu tapi Ki Sanak berdua dapat membuat perkiraan yang tidak mungkin saya paksakan,” kata pelan Agung Sedayu.
Dua pemimpin regu yang berlainan tingkat itu tidak lagi bertukar pandang. Mereka hanya mendengar suara hati masing-masing; di luar sudah beredar jawaban yang berbeda.
Suara langkah cepat terdengar dari luar. Dengan pakaian berhias darah dan lumpur, salah satu petugas sandi melaporkan dengan nada tergesa-gesa dan sorot mata cemas. “Ki Rangga, saya menemukan ini.” Dia menjulurkan tangan, sebuah lencana kecil dengan lambang khusus yang hanya dikenali segelintir prajurit saja.
Perubahan raut wajah cepat menyergap murid Kyai Gringsing itu. Dia mengenali benda itu sangat baik. Setelah menarik napas panjang, dia menenangkan petugas sandi tersebut, ”Tidak ada yang bersalah. Tidak perlu mencari sebab kematian. Segala akibat sudah barang tentu tidak dapat ditanggung sendirian oleh seseorang. Dia hanya menjalankan perintah, demikian pula yang menjadi korban.”
Kalimat itu tidak menenangkan, tapi juga tidak bisa dibantah.
Ki Lurah Sanggabaya melihat benda itu lebih dekat tapi tidak ada kata terucap. Ki Prana Aji segera memandang benda terjauh dari matanya.
“Hujan dan kabut, dua keadaan alam yang tidak terbantahkan,” ucap lirih Agung Sedayu. Lalu pada petugas sandi itu, dia berkata, “Berbenahlah. Jika ada keraguan, tinggalah di barak. Medan tidak akan dapat kau kendalikan bersama kegelisahan.”
“Saya, Ki Rangga,” sahut petugas sandi tersebut.
Agung Sedayu memintanya melaporkan diri pada Ki Lurah Sanggabaya jika keadaan hatinya benar-benar mengendap. Petugas tersebut mengangguk lalu menghilang di balik dinding ruangan.
Waktu merayap. Hujan hanya berkurang tapi menolak untuk berhenti. Ruangan menjadi gelap. Oh, rupanya mendung menjadi semakin tebal.
Seorang penghubung datang saat akhir pembicaraan. Dia membawa kabar; benturan keras antarpasukan berkuda di Kali Tinalah.
Agung Sedayu menanggapi dengan wajah dingin atau tenang, tapi memang sulit dijelaskan. “Persiapkan segalanya!” perintahnya yang menjadi penjelas.



