Lidah Api di Bukit Menoreh
Hari telah naik sepenuhnya. Kabut pagi menipis, membuka jalan-jalan setapak yang menghubungkan kediaman dengan lereng-lereng luar Bukit Menoreh. Di salah satu jalur itulah Ki Suta Jaladri bergerak, seorang diri. Dia satu-satunya bagin regu pembunuh yang lolos.
Tubuhnya menyimpan bekas pengeroyokan, tetapi langkahnya tetap terjaga. Dia tidak berlari, tidak pula tergesa. Jalan kaki adalah cara paling aman. Dengan sisa kemampuan sebagai prajurit Demak, meski telah belasan tahun ditinggalkan, Ki Suta Jaladri dapat membagi napas, menakar jarak, dan membaca medan. Satu ukuran waktu menanak nasi adalah hitungan waktu tempuh yang wajar baginya.
Sepanjang jalan, dia tidak menoleh ke belakang atau memandang kiri dan kanan. Semuanya sama, pikirnya, tidak berguna. Ki Suta Jaladri bergerak cukup cepat. Dia tidak membawa luka tapi kabar.
Gunung Kendil menerimanya dalam sunyi. Ki Suta Jaladari tidak kesulitan menembus rapatnya pengawas yang disebar di berbagai titik. Medan itu sangat dikenalnya. Setelah memastikan dirinya aman, Ki Suta Jaladri langsung menyampaikan laporan kepada Raden Atmandaru dan orang-orang kepercayaannya. Tidak berbelit, tidak diselubungi tafsir.
“Ki Gede berhasil dibunuh,” katanya.
Kalimat yang diucapkan tidak disertai perasaan berlebihan. Itu hasil lapangan yang sudah pasti. Ketenangan Ki Suta Jaldari terasa menambah bbobot laporan sehingga membuatnya terdengar lebih berat. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada dugaan atau kemungkinan. Hanya satu kalimat, Ki Gede mati.
Kabar itu segera dicatat, diteruskan, dan diperlakukan sebagai keterangan sangat penting.
Pada waktu yang hampir bersamaan, laporan-laporan lain mulai berdatangan. Petugas sandi yang disebar di berbagai titik membawa kabar serupa, dengan napas dan warna yang nyaris sama. Tidak semua berasal dari sumber yang kuat, tidak semua menyaksikan langsung. Namun berita itu telah terlanjur bergerak lebih cepat daripada bayangan.
Ki Gede telah mati.
Ki Gede dibunuh.
Ki Gede tidak diselamatkan.
Hari ini akan dikebumikan.
Dan keterangan lain yang senada dengan itu.
Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, dari gardu ke gardu, dari pasar ke pasar. Dia berubah rupa dari laporan menjadi keyakinan, dari keyakinan menjadi cerita, dari cerita menjadi kebenaran umum lalu berakhir sebagai kenyataan.
Berita kematian Ki Gede, yang lahir dari kabar setengah terang dan laporan yang saling menguatkan, menjelma menjadi ledakan di puncak Merapi. Tidak lagi dipertanyakan, tidak lagi ditunggu pembuktiannya.
Yang terhormat Pembaca Setia Blog Padepokan Witasem.
Kami mengajak Panjenengan utk menjadi pelanggan yang lebih dulu dapat membaca wedaran Kitab Kyai Gringsing serta kisah silat lainnya dari Padepokan Witasem. Untuk mendapatkan kelebihan itu, Panjenengan akan mendapatkan bonus tambahan ;
4 Buku Kitab Kyai Gringsing (PDF) dan Penaklukan Panarukan. Caranya? Berkenan secara sukarela memberi kontribusi dengan nilai minimal Rp 25 rb/bulan melalui transfer ke BCA 822 05 22297 atau BRI 31350 102162 4530 atas nama Roni Dwi Risdianto. Konfirmasi transfer mohon dikirimkan ke WA 081357609831
Demikian pemberitahuan. Terima kasih.
Luka Ki Jayaraga yang Berdarah dan Tak Berdarah
Dusun Benda masih menyisakan bau obat dan tanah basah ketika Ki Jayaraga dibaringkan di dipan bambu. Luka di sisi tubuhnya telah dibersihkan, tapi kain kasar itu tidak dapat menahan nyeri. Dia sadar sepenuhnya dengan sorot matanya jernih, hanya tubuhnya yang belum pulih.
Menjelang siang ketika pasar temawon, Ki Jayaraga sedang dalam perjalanan kembali ke pedukuhan induk ketika lelayu itu menyusulnya masuk ke dalam kedai.
Kabar kematian Ki Gede.
Berita yang tidak disampaikan dengan upacara kata, tidak pula dengan kesedihan yang dibuat-buat. Hanya laporan singkat dari petugas sandi pasukan khusus. “Ki Gede dibunuh. Kediaman kacau. Pasukan khusus turun tangan untuk menangani semuanya.”
Ki Jayaraga memejamkan mata sejenak. Napasnya tertahan, lalu dilepas perlahan. Tidak ada teriakan, tidak ada sumpah. Hanya satu gerakan kecil: jemarinya mengerat pada tepi dipan.
“Ki Rangga Agung Sedayu?” tanyanya pelan.
Petugas itu menggeleng. “Beliau masih tidak diketahui keberadaannya. Hingga saya berangkat, peristiwa itu masih belum mempunyai kejelasan.“
“Masih tidak diketahui keberadaannya?” ulang Ki Jayaraga sambil membuka mata. Di sana tidak ada amarah, hanya kelelahan yang bercampur penyesalan. “Kalau begitu,” katanya lirih, “ini bukan soal kematian semata.”
Dia sangat mengenal Agung Sedayu sejak hidup bersamanya, sejak tiga muridnya kalah dan ketika menuntut balas. Agung Sedayu, jika sesuatu sebesar ini terjadi tanpa penjelasan dan seolah dibiarkan, berarti ada siasat yang dipilih — dan siasat itu tidak dibagikan. Bahkan Ki Gede pun mungkin sudah dibatasi olehnya.
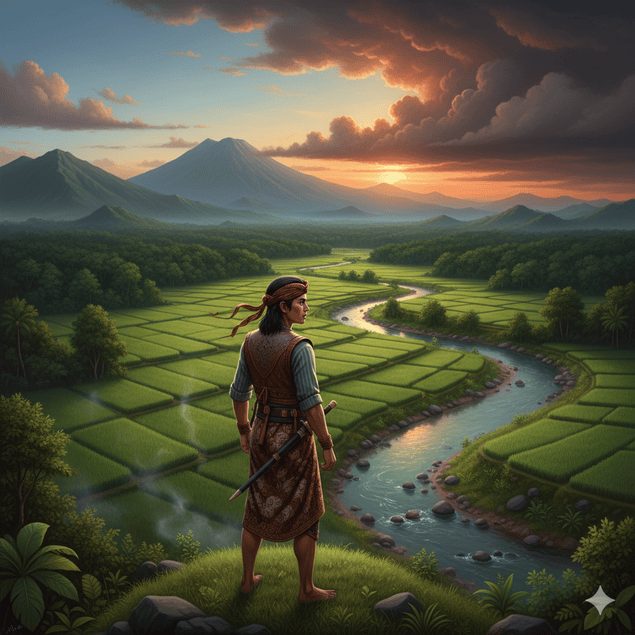
Glagah Putih, Antara Gusar dan Kecewa
Pagi di tepi hutan itu tenang, terlalu tenang. Cahaya matahari menerobos miring di sela batang-batang pohon, menyisakan bayang tipis di tanah lembap. Glagah Putih berdiri dengan kaki sedikit terbuka, dua tangannya terkulai di samping tubuh. Dia memandang ke arah dalam hutan pada sumber suara.
Langkah cepat terdengar dari balik semak. Seorang petugas sandi muncul, berhenti tiga langkah di depan Glagah Putih. Napasnya belum sepenuhnya teratur. Dia tidak langsung bicara. Dadanya naik-turun, matanya ragu, lalu menunduk.
Glagah Putih menoleh perlahan. Alisnya berkerut tipis. “Ada apa?” tanyanya pendek.
Petugas itu menggeser kakinya, ujung jari tangannya saling menekan. Dia mengangkat wajah, tapi pandangannya tidak bertahan lama.
“Ki Lurah,” katanya, suaranya tertahan. “Ada kabar… pedukuhan induk.”
Glagah Putih tetap diam. Bahunya tidak bergerak, tapi rahangnya mengeras. Meski segenap jalan pikirannya menjadi sangat sibuk.
“Katakan,” ujarnya.
Petugas sandi menelan ludah. “Ki Gede… terbunuh pagi tadi.”
Udara seperti berhenti sesaat.
Glagah Putih tidak bereaksi. Matanya tetap lurus ke depan, tapi pertahanan dirinya runtuh. Jari-jarinya perlahan mengepal, lalu terlepas lagi. Dia menarik napas, pendek dan tertahan.
“Siapa?” tanyanya. Suaranya datar, tapi ada retakan kecil di ujung kata.
Petugas itu menggeleng pelan. “Belum jelas. Luka senjata tajam. Tubuhnya ditemukan—”
Glagah Putih mengangkat tangan, menghentikan kalimat itu di tengah. Dia berbalik setengah badan. Pandangannya menyapu pepohonan, seolah mencari sesuatu yang tak mungkin terlihat. Napasnya kini lebih berat, tidak teratur.
“Saya terima,” katanya dengan wajah menunduk. “Ki Sanak dapat melanjutkan kegiatan lainnya.”
Petugas sandi mundur cepat, menghilang di balik semak.
Glagah Putih tetap berdiri. Rahangnya mengeras semakin kuat. Tangannya mengepal penuh kali ini. Ada kegusaran yang naik, bukan meledak, menekan dari dalam tapi belum menemukan jalan keluar.
Ledakan Sukra
Sementara itu, Ki Demang Brumbung berdiri dengan tangan bersedekap, sorot matanya lebih gelap dari biasanya. Dia tidak menyembunyikan kegundahan, namun juga tidak meledakkannya.
“Kita ini apa?” katanya akhirnya, suaranya berat. “Orang kepercayaan atau sekadar bidak?”
Tidak ada yang menjawab. Dua pasukan khusus di sampingnya hanya memandang ke bawah. Ki Demang Brumbung menunduk sesaat. Mereka bertiga sama-sama mampu menahan diri tapi bukan berarti tidak terluka.
“Aku tidak mempersoalkan siasatnya,” lanjut Ki Demang Brumbung. “Aku mempersoalkan mengapa kita tidak diberi tahu. Bahkan sekadar peringatan.”
Salah seorang dari mereka berkata, “Ki Rangga bertindak lain dari yang kita kenal dari beliau selama ini.”
Di titik itulah mereka sepakat—tanpa perlu sumpah atau isyarat khusus : bukan untuk memberontak; bukan untuk menuduh; tapi penjelasan.
Sukra datang tanpa aba-aba.
Langkahnya cepat, napasnya tidak teratur. Wajahnya pucat, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam—sesuatu yang telah lama disimpan.
“Kalian semua tahu?” katanya, suaranya bergetar. “Kalian tahu dan masih bisa duduk diam?”
Tidak ada yang langsung menjawab.
Sukra memandang wajah langsung beradu mata satu per satu. Pandangannya menyapu Ki Demang Brumbung dan orang-orang lain di sekitarnya. “Belasan tahun, aku hidup bersama Ki Lurah,” katanya. “Beliau bukan lagi menjadi orang lain bagiku.”
Suaranya naik sedikit, bergetar. “Beliau tidak pernah meninggalkanku dalam gelap. Tidak pernah.” Dia berhenti, mengatur napas. “Tapi sekarang… tidak ada yang tahu keberadaannya di saat Ki Gede seda ing dalem, tertikam! Pada saat lawan mencari kelengahan, kita disuruh percaya tanpa penjelasan?”
Ki Demang Brumbung berdiri. “Sukra—”
“Tidak!” Sukra memotong. Untuk pertama kalinya, dia tidak menunduk pada nama besar atau kedudukan. “Aku bisa menerima siasat apa pun. Aku bisa menerima jika Ki Lurah memilih jalan paling berbahaya. Aku rela bunuh diri jika beliau meminta, tapi aku tidak bisa menerima jika kami—yang hidup bersamanya—dianggap tidak perlu tahu apa pun!”
Bahkan embung pun tak ingin beriak ketika Sukra selesai bicara. Sunyi. Tidak ada yang menegur. Karena semua tahu: ledakan itu bukan pembangkangan. Itu luka.
Sukra mengusap wajahnya kasar. “Jika Ki Lurah memang punya rencana,” katanya lebih pelan, “maka ia harus menjelaskannya. Kalau tidak… Ki Lurah akan kehilangan lebih banyak daripada musuh.”
Tidak ada yang menyangkal bahwa pada hari itu, di berbagai tempat yang terpisah, orang-orang yang paling dekat dengan Agung Sedayu sampai pada satu kesadaran yang sama: bukan kematian Ki Gede yang paling berbahaya, tapi Agung Sedayu yang seolah kehilangan akal dan suara.



