“Ki Wedoro Anom dan Ki Demang Brumbung. Mereka berada di dalam dua kelompok yang berbeda. Sukra berpasangan dengan Ki Demang Brumbung, sedangkan Ki Wedoro Anom bersama Ki Jayaraga,” terang Agung Sedayu. Dia menatap Prastawa sebentar kemudian berkata, “Aku harap tidak ada yang menganggap keputusan itu termasuk berlebihan. Tidak, aku mempunyai alasan dan harapan kuat bahwa Sukra dapat menjadi salah seorang yang dapat diandalkan oleh tanah ini pada masa mendatang.”
Prastawa mengangguk-anggukkan kepala seperti dapat menerima keputusan Agung Sedayu. Sesaat dia diam sejenak, lalu bertanya, “Apakah nantinya Sukra tidak menjadi kelemahan atau mungkin malah memberatkan Ki Demang Brumbung?”
“Pergaulannya yang cukup dekat dengan Glagah Putih serta segala yang diperolehnya selama di Kepatihan telah membuatnya berkembang pesat,” Agung Sedayu menjelaskan alasannya. “Dia banyak mengalami kesulitan saat menyesuaikan diri tapi dia mampu melewati semuanya dengan sangat baik.”
Pandan Wangi menambah keterangan Agung Sedayu. Katanya, “Di Watu Sumping, aku melihat Sukra yang berbeda dengan keadaannya setahun atau sebulan yang lalu. Pada pertempuran itu, dengan segala sesuatu yang menjadi ciri khasnya, Sukra menjadi salah seorang yang menjadi penyemangat ketika sebagian dari kami mengalami kemunduran jiwani. Bagiku, itu adalah nilai lebih yang menandakan bahwa Sukra tidak mudah terpancing rasa takut.”
“Dulu, kita mempunyai Kyai Gringsing dan Ki Waskita sebagai orang-orang yang selalu berada di samping saya pada setiap dera gelombang yang melanda Tanah Perdikan,” ucap Ki Gede dengan suara lirih. “Hari ini, kita mempunyai Mpu Wisanata dan Ki Jayaraga yang hampir dapat menggantikan keberadaan Kyai Gringsing serta Ki Waskita. Memang tidak dapat dikatakan benar-benar menggantikan tapi Tanah Perdikan Menoreh ternyata memang tidak pernah sendiri.” Ki Gede kemudian menarik napas dalam-dalam. Selintas kenangan berjalan pelan di dalam pikirannya. Dia tidak boleh larut pada pusaran masa lalu, Tanah Perdikan Menoreh sedang membutuhkan perhatian penuh darinya, pikir Ki Gede Menoreh.
Baik Agung Sedayu, Pandan Wangi maupun Prastawa menyadari bahwa mereka tidak dapat segera bersuara untuk mengingatkan Ki Gede. Mereka mendengar dan juga melihat raut wajah Ki Gede yang sepertinya menggambarkan bahwa pikiran pemimpin Tanah Perdikan itu tidak sedang bersama dengan raganya. Diam menjadi pilihan terbaik hingga keadaan mempunyai kecenderungan berbeda.
Sadar bahwa tiga orang sedang menunggu arahan darinya, Ki Gede lantas berkata, “Marilah, kita kembali pada permasalahan.” Meski mengatakan itu tapi Ki Gede tidak lantas mengungkap pendapat melainkan menarik napas dalam-dalam. Dia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.
Agung Sedayu tanggap dengan keadaan. Sebelum dia datang kembali ke Tanah Perdikan bersama Pandan Wangi, pikirannya sudah sibuk dengan berbagai siasat yang paling mungkin untuk diterapkan. Raut wajah Agung Sedayu terkadang tampak tegang, tapi sebentar kemudian berubah menjadi tenang. Perubahan yang menunjukkan bahw senapati Mataram itu benar-benar larut dengan arus pemikiran yang sedang baku hantam di dalam benaknya.
“Saya setuju dengan yang baru saja diungkapkan oleh Ki Gede bahwa mereka mundur dari Karang Dawa dan Watu Sumping bukan karena mereka adalah pengecut. Ada sebab lain yang yang juga masuk akal yaitu sengaja atau semacam pertaruhan belaka. Baiklah, saya anggap mereka mundur itu bukan untuk menyerah. Bagaimanapun, saya selalu beranggapan bahwa geger Alas Krapyak adalah akibat yang pertama. Gerakan Raden Atmandaru adalah rangkaian yang cukup panjang dan dia benar-benar sabar menunggu saat yang tepat,” ucap Agung Sedayu. “Sebelum memenuhi panggilan Ki Gede, saya membentuk dua kelompok kecil sudah bergerak menuju dua tempat yang agak berjauhan. Maksud saya, pasukan khusus tidak boleh tergesa-gesa karena pemetaan belum sepenuhnya dapat dilakukan. Ini pula yang menjadi alasan kami terkesan membiarkan Ki Garu Wesi melenggang. Bisa jadi sudah beredar anggapan kita takut dengan mereka. Maka, saya minta bantuan kalian berdua untuk meyakinkan pengawal agar tetap menunggu perintah dari Ki Gede.”
Pandan Wangi dan Pastawa mengangguk setuju.
Kemudian Prastawa berkata, “Saya kira memang lebih baik kita menunggu hingga pergerakan mereka tampak lebih jelas.”
“Tapi kita tidak dapat menunggu dengan waktu tanpa batas,” timpal Pandan Wangi lalu menoleh pada Agung Sedayu. “Kakang, menunggu sudah jelas menjadi pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Lebih-lebih mereka menyebarkan ucapan-ucapan yang sangat mengganggu ketenangan rakyat Perdikan. Sambil melakukan itu, mereka dapat membuat sasaran baru. Saat ini, saya belum siap mengatakannya.”
Ki Gede terpaku mendengar kata-kata Pandan Wangi. Jika melihat peristiwa yang telah lewat dan geger Alas Krapyak disebut sebagai hasil atau akibat yang pertama, bukankah ada kemungkinan bahwa dirinya menjadi sasaran yang kedua? Apakah itu maksud dari yang dikatakan Pandan Wangi bahwa dia belum siap mengatakannya?
Waktu mengapung lambat hingga tak terasa hidangan di atas meja menjadi dingin. Tiga pemuka Tanah Perdikan Menoreh yang berada di pringgitan seakan mempunyai pendapat dan perasaan yang sama dengan Ki Gede.
Prastawa mengangkat suara kemudian, “Ada benarnya, ada benarnya.” Dia seolah-olah sedang bicara dengan dirinya sendiri. Agung Sedayu dan Pandan Wangi segera melihat ke arahnya dengan alis berkerut.
“Oh, maaf,” kata Prastawa cepat. “Saya pikir Pandan Wangi membuka kemungkinan yang dapat saja dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pantas. Seandainya seseorang ingin merebut suatu wilayah, maka hal yang paling masuk akal dilakukan adalah mengepung lalu mengikis daerah yang menopangnya.”
Buku ketiga menempatkan Tanah Perdikan Menoreh dalam pusaran konflik terbuka. Gerakan makar yang selama ini bergerak di balik bayang mulai menampakkan wujudnya, memaksa para tokoh utama mengambil sikap yang tak lagi bisa ditunda.
Di tengah ketegangan itu, muncul benturan langsung antara kepentingan kekuasaan, kesetiaan pribadi, dan harga diri perguruan. Nama Agung Sedayu, Sangkal Putung, serta pihak-pihak yang selama ini hanya disebut lirih, kini menjadi pusat pertarungan wacana dan senjata.
Buku ini memperlihatkan bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai perang besar, melainkan sebagai serangkaian provokasi, tuduhan, dan pengkhianatan kecil yang terakumulasi. Pertarungan tidak hanya terjadi di medan laga, tetapi juga dalam pikiran: siapa yang patut dipercaya, siapa yang diam-diam menunggu saat menusuk dari belakang
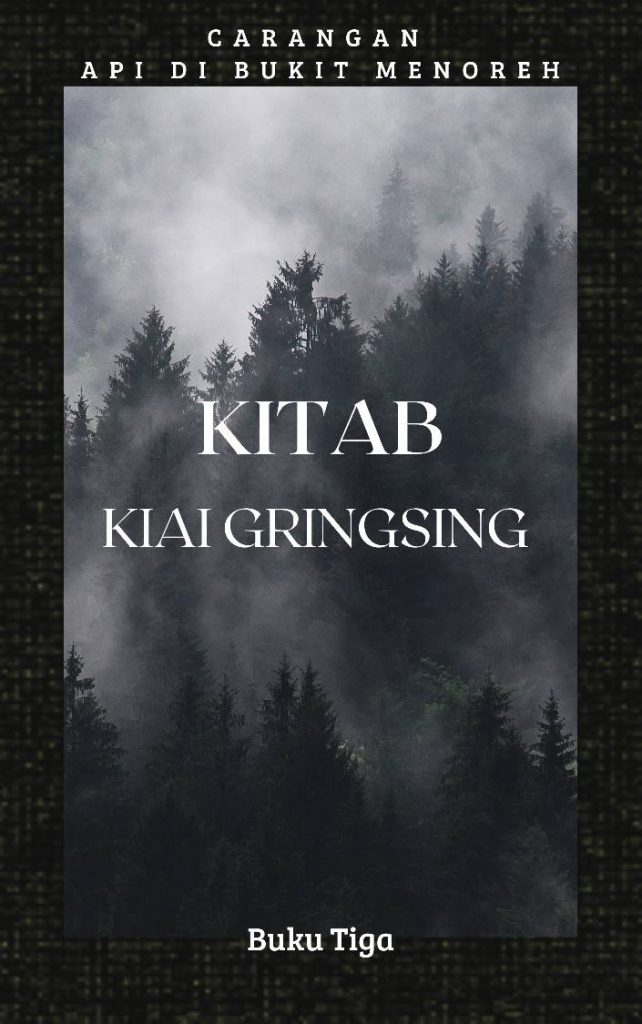
Agung Sedayu membenamkan wajah sesaat. Katanya, “Meski tidak secara langsung, tapi mereka memang dapat dikatakan mempunyai peran dan juga bertanggung jawab pula pada wafat Panembahan Hanykrawati. Yang tidak mereka perhitungkan adalah keadaan di kotaraja yang begitu rumit untuk diuraikan. Walau terdengar kabar bahwa ada kubu yang berlawanan tapi yang pasti adalah tidak ada perselisihan yang berujung kekerasan. Aku kira mereka, Raden Atmandaru ini, sedang berharap terjadi kekacauan sebagai jalan masuk merebut Mataram.
“Setelah kegagalan, anggaplah begitu, di Sangkal Putung, mereka mengarahkan pandangan ke sini, ke Tanah Perdikan ini. Lalu, apa perkiraan yang muncul dalam pikiran kita? Mengapa Tanah Perdikan? Mengapa bukan Jati Anom atau kademangan lain yang masih dekat dengan kotaraja? Tentu setiap orang mempunyai pendapat, tapi saya lebih cenderung berpikir apabila mereka berhasil merebut Tanah Perdikan Menoreh, maka jarak adalah satu-satunya alasan masuk akal. Anggaplah mereka berhasil, jarak yang cukup jauh memberi waktu bagi mereka untuk membuat persiapan perang berikutnya, menggalang bantuan atau bahkan mengembangkan diri menjadi semakin kuat.”
“Dengan kata lain, mereka dapat membuat pemerintahan tandingan di sini?” tanya Prastawa demi meyakinkan dirinya sendiri.
Agung Sedayu mengangguk, jawabnya, “Tidak menutup kemungkinan untuk itu. Mereka sepertinya sudah mempunyai orang-orang yang dianggap berkemampuan untuk tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan.”
“Lagipula wilayah ini juga bukan kawasan terpencil atau terasing,” kata Pandan Wangi lirih. “Jalur perdagangan dan hubungan dengan daerah lain sudah terjalin serta terjaga puluhan tahun lamanya.” Kemudian dia menatap wajah Ki Gede dengan pandangan sayu. Sambil menahan gemuruh dalam hatinya, dengan suara sedikit terputus-putus, Pandan Wangi bertanya pada Agung Sedayu, “Mungkinkah mereka akan mendatangi ayah demi wilayah ini?”
“Seperti yang disebutkan Ki Gede, Ki Kapat Argajalu pernah melakukan itu, tanpa rasa malu, meminta kekuasaan secara terus terang. Ki Gede menolak dengan sebab yang sangat kuat lalu kita terlibat dalam benturan,” ucap Agung Sedayu. “Maka, Raden Atmandaru pun dapat berbuat yang sama dengan orang itu.”
“Jadi, tidak menutup kemungkinan pula mereka langsung menusuk jantung pedukuhan induk, kemudian…,” ucapan Prastawa terputus saat dia sadar atas yang akan terucap!
Pandan Wangi menutup muka. Agung Sedayu melengos lalu mengepalkan tangan diam-diam. Mengapa juga harus mengucapkan itu? Pada waktu sebelumnya, bukankah Ki Patih Mandaraka pun tak lepas dari serangan yang mematikan dan dilakukan secara berkelompok? Mungkin benar seandainya Raden Atmandaru menjadikan Ki Gede Menoreh sebagai sasaran pembunuhan pemimpin setelah Panembahan Hanykrawati, tapi apakah harus diucapkan dengan terang benderang?
Prastawa benar-benar kesulitan menempatkan diri setelah mengucapkan itu hingga Ki Gede kemudian berkata, “Sudahlah. Aku dapat menerima kau berkata seperti itu karena maksud ucapanmu pun menjadi peringatan bagi kita semua.” Ketegangan pun sedikit menurun setelah Ki Gede bersuara.
Pemimpin Menoreh itu kemudian bertanya pada Agung Sedayu, “Apakah sudah ada perkembangan kabar dari Ki Jayaraga atau Sukra?”
”Hingga saya keluar dari gerbang barak pasukan, saya belum mendapatkan kabar. Tapi petugas penghubung tidak akan bergeser ke sini jika berita tidak dianggap begitu penting oleh Ki Lurah Sanggabaya atau Glagah Putih,” jawab Agung Sedayu.
“Oh, jadi Glagah Putih tidak dalam tugas pengamatan?” tanya Ki Gede.
“Tidak, Ki Gede. Keberadaannya akan lebih dibutuhkan jika tetap di dalam barak untuk saat-saat dekat ini,” ucap Agung Sedayu.
Empat orang itu menghentikan pembicaraan sebentar. Mereka menikmat hidangan yang sudah dingin demi mengisi ulang tenaga yang sedikit terkuras karena perasaan dan pikiran. Percakapan ringan pun hadir di antara mereka. Perkembangan hasil panen, perdagangan antar wilayah dan sebagainya.



