Ada kemungkinan yang dapat terjadi bagi mereka bertiga di dalam kedai yang terletak di dusun yang terpencil itu. Membiarkan diri tertangkap agar mendapatkan jalan untuk menguak tabir yang menutup tokoh di balik penikaman Raden Trenggana, atau berterus terang mengenai jati diri mereka. Meski demikian, keterangan yang terbuka itu pun mungkin menjadi percuma karena orang-orang sekitar mereka sudah pasti tahu sebelumnya. Memang tidak ada pilihan lain karena mereka bertiga harus tetap dapat tiba di Demak sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Ki Tumenggung Prabasena telah memberitahukan pada Gagak Panji dan Arya Penangsang, bahwa orang-orang yang menghendaki kematian Raden Trenggana telah mendapatkan tempat untuk menyembunyikan diri, kemudian keluar pada saat yang mereka kehendaki.
Itu adalah suasana yang janggal pada siang hari di dalam kedai. Sebelum mereka bertiga memasukinya, orang-orang bercakap ramai hingga terdengar seperti dengung lebah. Mendadak seluruhnya menekan suara ketika tiga orang asing datang dengan sikap tubuh yang tidak biasa.
Tidak ada waktu lagi bagi Arya Penangsang, Gagak Panji dan Ki Prabasena untuk berunding walau sebentar. Hidangan yang dipesan pun seolah tidak lagi menarik minat untuk dinikmati ketika paras wajah dan sorot mata aneh mulai terpusat pada mereka. Dalam keadaan demikian, Gagak Panji tetap tidak merubah sikap dan gaya bicaranya. Ki Prabasena tampak perlahan-lahan mencicipi makanan dengan pandangan waspada. Sementara itu, Arya Penangsang lekat menatap pada arah pintu seakan sedang menunggu kedatangan seseorang. Mungkin Arya Penangsang memang sedang mengharapkan seseorang muncul dari luar kedai, dan bukan itu yang terjadi kemudian.
Seseorang bertubuh kekar kemudian berkata dengan suara lantang, “Aku tidak melihat seseorang atau sebuah rombongan yang menyeberangi jembatan. Apakah ada dari kalian yang tahu sebabnya?”
“Kyai, mungkin bukan mereka atau orang itu yang dikabarkan akan menyeberang karena memang tidak ada yang melintasinya, kecuali para petani yang pergi ke ladang,” jawab seseorang yang kelihatannya berusia pertengahan dua puluh tahun.
“Maka dari itu, aku bertanya tentang sebabnya, Poh Kecik. Karena hanya sebangsa siluman saja yang keluar dari hutan tanpa terlihat,” sahut orang bertubuh kekar yang kemudian ditimpali suara orang-orang tertawa. Lantas orang itu melanjutkan, “Yangada adalah sebuah perjalanan panjang dengan beban yang sangat berat.”
Suasana mendadak senyap dan seakan memberi kesempatan pada lelaki kekar itu untuk berkata lebih banyak lagi.
Benar, lelaki yang sekarang menjadi pusat perhatian lantas mengatakan, bahwa dia mendengar dari percakapan yang riuh sepanjang bibir pantai utara. “Sebuah kabar yang akan menggemparkan ibukota Demak. Ini akan menjadi berita besar karena seseorang yang sangat berpengaruh akhirnya menemui ajal melalui jalan yang tidak terduga.” Dia berjalan menuju bangku yang berjarak sekitar lima langkah dari Ki Tumenggung Prabasena, katanya kemudian, “Angkatan perang Demak mendapatkan perlawanan hebat dari para prajurit Blambangan. Sudah tentu itu adalah sesuatu yang mengacaukan segala siasat panglima Demak. Di laut, Demak bertemu lawan yang sangat hebat. Di darat? Ternyata Demak lebih memilih duduk bersambung punggung sambil mencari kutu-kutu yang berkeliaran di rambut.Tentu, aku tidak sedang mengatakan ingin merendahkan atau meremehkan kemampuan angkatan darat mereka, tapi nyatanya? Tidak terjadi pertempuran di darat.”
“Ki Mojo Tamping,” kata seseorang yang duduk di dekat Adipati Arya Penangsang, “apakah kita telah mendapatkan alasan mengenai sikap mereka yang tiba-tiba berubah menjadi penakut?”
“Sebab yang tepat, tentu, aku tidak tahu dan mustahil aku mengarangnya untuk kalian. Namun, kegagahan angkatan perang Demak pun terlampau tinggi untuk dibicarakan saat ini. Mereka tidak ubahnya dengan wilayah manca. Demak mulai gentar ketika melihat keadaan di dalam istana mereka.”
Orang-orang saling berpandangan. Terbayang matahari Demak yang mulai terbenam di dalam pikiran mereka. Mungkinkah Demak akan mendekati masa suram? Itu adalah perjalanan yang singkat untuk sebuah pemerintahan yang dibangun oleh keturunan Maapahit. Walau demikian, mereka tetap bersorak sekalipun bibir mereka mengatup rapat.
“Apakah mereka tertinggal. Ki Mojo Tamping?” tanya Poh Kecik.
“Tidak mungkin,” sahut orang yang berdekatan dengan Adipati Arya Penangsang.
“Ki Bajijong berpendapat benar. Benar bahwa mereka tidak tertinggal, dan tidak juga terlambat meninggalkan Blambangan. Mereka mungkin menempuh jalan sesat,” ucap Ki Mojo Tamping dengan nada dingin.
“Poh Kecik, mengapa kau pikir mereka bisa tertinggal?” tanya Ki Bajijong.
“Kerusuhan di Panarukan pastilah membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk penyelesaiannya. Aku kira begitu, maka sungguh masuk akal bila ada satu atau dua orang yang ketinggalan kapal,” jawab Poh Kecik.
“Poh Kecik, apakah engkau tidak melihat?” Ki Mojo Tamping bertanya tanpa membuat gerakan.
Poh Kecik menautkan alis, memandang orang-orang di sekitarnya. Ya, ada tiga orang asing yang turut duduk bersama mereka di dalam kedai. “Aku hanya harus meneruskan sandiwara,” desisnya dalam hati. Untuk sesaat, Poh Kecik duduk terpaku namun nalarnya bekerja cepat untuk menyusun langkah-langkah atau siasat dengan cekatan.
Mereka, selain Adipati Jipang bertiga, tidak akan dapat duduk tenang selama belum menuntaskan perintah yang diteruskan oleh Lembu Jati. Diam-diam mereka memupuk semangat dengan mimpi dan harapan besar. Bagi mereka, itu bukan omong kosong karena terobosan Ki Danupati telah memberikan hasil. Keberanian adalah perjuangan untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan, demikian hati mereka membulatkan tekad! Tidak ada waktu dan alasan untuk berhenti pada dermaga yang tidak pantas menjadi sandaran mimpi, dan itu adalah rasa malas serta takut mati! Bagi mereka, pada waktu itu, kematian adalah perjalanan yang cukup megah.
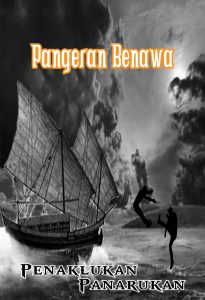
Delapan orang berada di depan dan belakang, serta di samping Gagak Panji. Ki Tumenggung Prabasena terlihat seolah sedang diapit oleh enam orang yang sepertinya berasal dari sebuah perguruan atau prajurit bayaran. Sementara Adipati Jipang, Arya Penangsang, seakan terlepas dari pengamatan orang-orang yang menjadi calon lawannya. Mereka semua masih berada di atas bangku masing-masing.
Pada saat hari menjelang siang, matahari semakin terik dan udara terasa kian panas menyapa badan jalan yang belum dipadatkan. Debu membubung tinggi ketika angin menyapu permukaan dengan sapuan yang seolah berlambarkan api. Suasana dusun begitu lengang. Para petani bertelanjang dada mengerjakan ladang dan pategalan mereka. Mencabuti rumput, membalikkan tanah, membakar rumput-rumput kering yang telah ditumpuk setinggi lembu jantan.
“Apakah sekarang sudah waktunya mencabuti lalu membakar sarang ular?” tanya Ki Bajijong dengan mata tajam menatap Ki Mojo Tamping.
“Tentunya ular-ular itu tidak akan mampu menggeliat keluar sarang. Meskipun begitu, aku lebih suka untuk menunggu sedikit lebih lama,” sahut Poh Kecik.
Sama sekali tidak ada tanggapan dari orang-orang yang berada di di dalam kedai. Mereka tahu maksud ucapan bersahut antara Ki Bajijong dan Poh Kecik, tetapi perintah tertinggi adalah Ki Mojo Tamping. Mereka sedang menunggu satu kalimat dari lelaki yang mempunyai pembawaan tenang itu.



