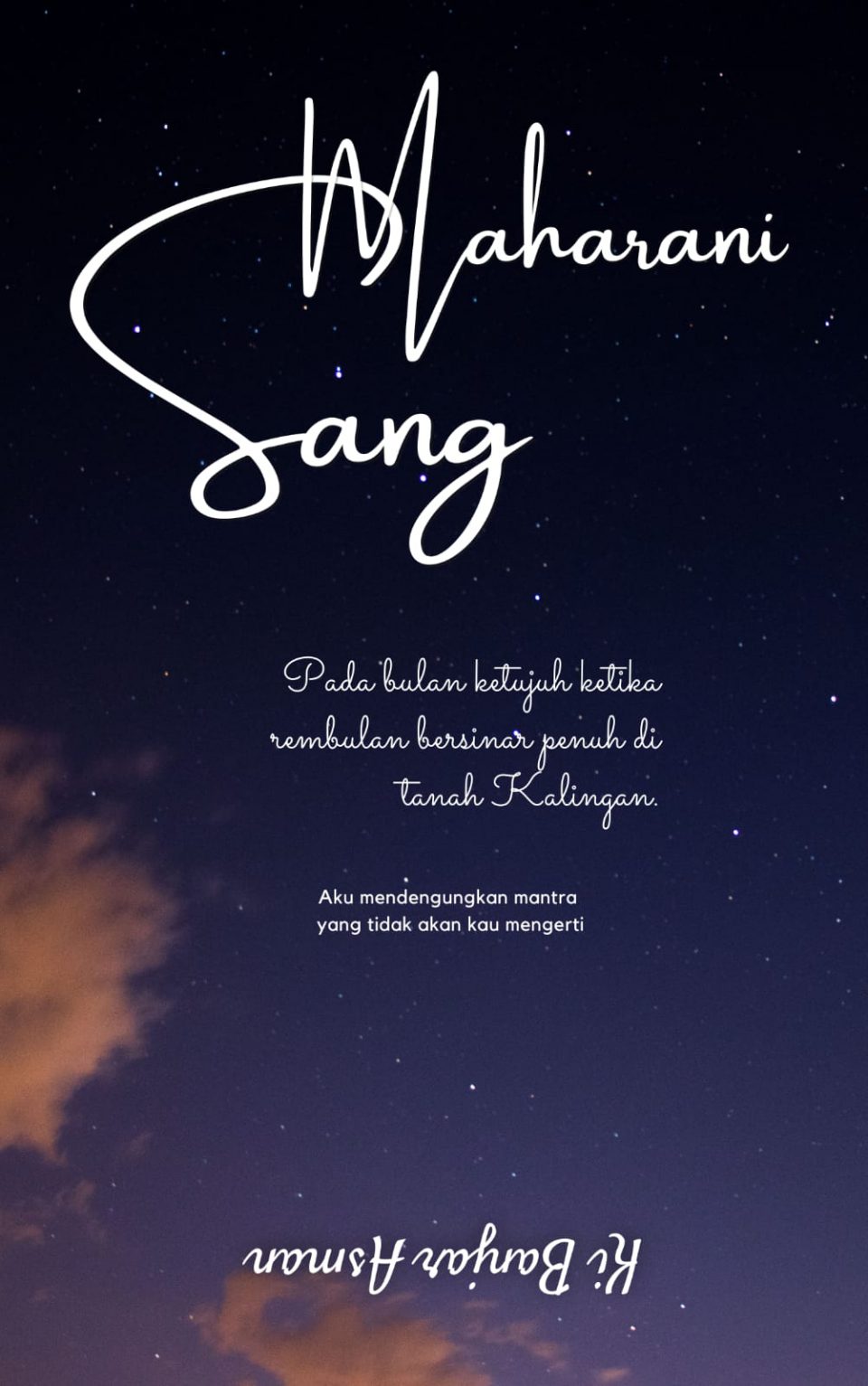Datanglah waktu yang dimaksudkan Mpu Pali. Datanglah ia padaku yang sedang berjibaku mempertahankan liang sempit dengan tubuh membeku. Ayahku adalah seorang penguasa, seorang ratu tetapi ia tidak akan mampu melindungi kehormatan yang berada di tengah-tengah pangkal pahaku. Itu bukan tugasnya, aku tahu.
Aku telah menjadi pusat keributan. Aku ingin memenggal kepala orang-orang yang berteriak kasar padaku.
Aku ingin menendang kepala orang-orang yang berkata keji tentang ayahku.
Aku ingin mengunyah jantung sambil minum darah mereka di bawah cahaya suram bulan yang telanjang.
Aku seperti telah melihat peristiwa itu dan tidak merasa enggan untuk membayangkannya. Aku pikir wajar bila aku berkeinginan menghisap darah mereka setelah segala yang terjadi pada pagi ini.
Dalam bayanganku.
Aku bergerak tenang sambil meloncat ke depan, ke samping kiri dan kanan, membalikkan tubuh, melenting lalu menangkis setiap serangan dengan berbatang-batang sujen terselip di antara jemari tangan. Denting nyaris kerap terdengar walau aku bersenjata dengan bahan bambu.
“Hey!” aku berseru pada lawan-lawanku. “Aku ingatkan agar kalian segera mengambil jalan selamat. Ketahuilah, aku tidak ingin melihat kalian menangisi setiap tetes darah yang keluar dari dada kalian yang berlubang. Segera!”
Seorang dari mereka menyahut, “Aku hanya ingin menemanimu barang semalam. Aku ingin melihat belahan paha dan dada yang menggantung di bagian depan tubuhmu. Aku ingin menghisap setiap yang keluar dari celah-celah tubuh. Aku ingin mereguk wangi itu.”
“Aku tahu dan aku dapat mengerti keinginanmu. Aku tahu dan aku ingin engkau mengerti bahwa aku ingin merasakan kesenangan yang sama denganmu. Kita akan bersama-sama melakukannya,” jawabku lalu berkelebat lebih cepat. Sekejap kemudian, mereka berteriak-teriak dengan nada suara yang menjemukan. Aku kira benar jika itu menjemukan. Aku kira benar bahwa suara mereka keluar dari kerongkongan yang tersayat sujen dan sewaktu kepala mereka nyaris terpisah, seketika itu mereka mengeluarkan nada-nada sedih. Aku jemu mendengar suara-suara memohon ampunan. Bukankah aku telah meminta mereka untuk pergi meninggalkan gelanggang perkelahian?
Mereka tidak percaya? Itu salah mereka.
Musuh-musuh telah terbabat habis. Sedikit yang bertahan hidup. Ibu dan Empu Balitung seperti sengaja membiarkan mereka hidup.
“Dyah Murti!” seru ibuku dengan nada yang sangat aku kenal. “Berhentilah menyiksa mereka.”
Aku membuka mata. Sungguh mengerikan! Aku melihat sedikit orang yang terkapar sedang melolong kesakitan. Mereka seolah berteriak-teriak dan semuanya ditujukan padaku bahwa aku menjadi gila. Namun aku tidak dapat mendengar suara mereka.
“Ampunilah mereka,” ucap Empu Balitung.
Apakah aku harus peduli pada mereka? Bukankah mereka telah menghina segala yang menjadi milikku? Apakah mereka lebih baik hidup sebagaimana mestinya? Ya, barangkali mereka dapat mengubah jalan hidup. Siapa yang menjadi penjamin? Bila mereka sanggup berbuat keji padaku, bukankah anak-anak gadis di dusun-dusun dan wanua sedang terancam bahaya besar? Mereka adalah serigala keji penghisap lendir yang membasahi kemaluan para wanita. Mereka pula yang akan menyebabkan ratusan anak menjalani hidup tanpa lelaki yang disebut sebagai ayah. Tidak, aku tidak ingin memaafkan mereka.
“Apa mereka memang pantas melanjutkan hidup, Ibu?”
“Di hadapan ayahmu, mereka adalah sekumpulan lalat tolol. Dan seharusnya pula engkau memandang mereka sebagai lelaki yang tidak mempunyai harga diri. Agar mereka menjadi berharga di depan ayahmu, dan juga dalam pandanganmu, maka berilah mereka izin untuk melanjutkan hidup. Berilah mereka tanggung jawab,” jawab Lis Prabandari. Perempuan itu, sungguh, sangat membanggakan!
Benarkah? Benarkah mereka akan menjadi lelaki yang tangguh dan jantan?
“Ibu, mereka akan mengulang perbuatan dengan menyelinap, memasuki pekarangan orang, merenggut setiap perempuan yang terlihat, lalu keluar dusun tanpa sedikit pun yang tersisa. Tidak akan ada kehormatan bagi perempuan pada setiap dusun yang didatangi mereka.”
“Pada pagi ini, di tepi hutan ini, mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa keturunan Rakai Panangkaran bukan perempuan yang dapat diremehkan. Mereka akan menyebarkan berita, tentu disertai dendam dalam hati masing-masing, bahwa perempuan yang dipaksa Kayu Merang bukan perempuan biasa. Dan itu akan menjadi baik untukmu, Dyah Murti,” kata Empu Balitung.
Aku belum dapat memutuskan. Aku belum membuat penilaian. Aku hanya memandang tanah yang menjadi tempat kaki berpijak.