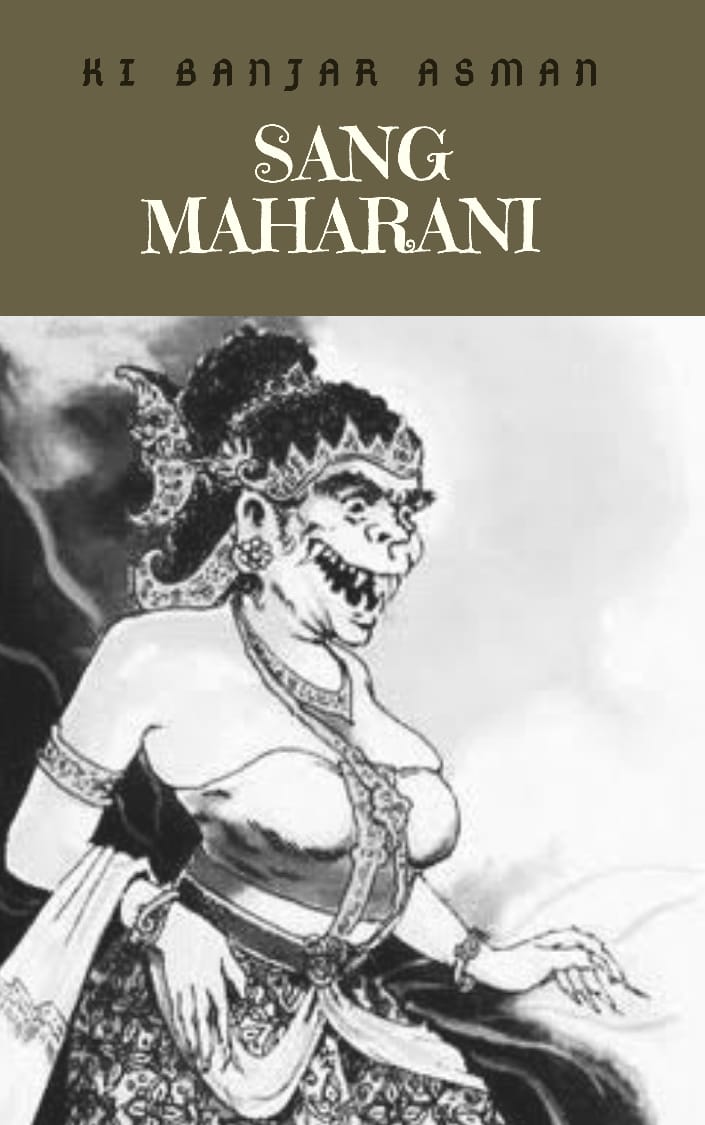Seakan ada sepasang mata yang memandangku dengan wajah yang bergaris kebengisan. Lantas pemilik wajah itu berkata, “Masa mudamu yang terhimpun di Kalingan bukanlah sebuah waktu yang tergenang tanpa arti. Ketika kau melihat arak-arakan yang mengiringi kepergian orang mati, kau menutup mata perlahan. Pada waktu itu kau merasakan sepasang lututmu tidak lagi mampu menyanggah tubuh. Pada waktu yang sama kau pun bertanya pada Han Rudhapaksa, ke mana mereka pergi? Seorang Dyah Murti kemudian berjingkat pelan, mengikuti kepergian orang-orang yang tegar melangkah menuju gerbang dunia orang-orang mati.”
Aku mendiamkan diri dengan cara yang tidak biasa. Aku ingin menambahkan, sebenarnya, bahwa aku tidak menyimpan keinginan untuk membangunkan mereka yang berlalu beku di depan mataku. Untuk apa?
Bagian diriku yang lain, yang mempunyai wajah bengis, kemudian melanjutkan ucapan, “Sapalah dan katakan segala yang baik ketika kau duduk di sebuah padang. Akan tiba waktunya bagimu untuk bersimpuh di tengah padang yang dipenuhi pusara-pusara yang menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang banyak orang. Ketika itu terjadi, Dyah Murti akan kehilangan kemampuan dan keperkasaan yang mengagumkan orang yang mengenalnya.”
“Pusara,” aku bergumam. Aku bertanya pada diriku yang lain, “Apakah pusara mampu menyimpan rahasia-rahasia yang kadang masih berbaur di angkasa bersama burung-burung liar tanpa mahkota? Apakah pusara dapat disebut sebagai penjara untuk keinginan-keinginan yang belum terlampiaskan?”
“Pusara adalah batas yang memupus kesenangan. Namun pada saat yang sama, pusara adalah sebuah ibarat tentang embun yang menyejukkan.”
Aku terhempas kembali setelah melayang-layang di atas ribuan gundukan tanah yang berserak di kaki bukit. Aku terdampar, bersandar pada sebatang pohon berdaun layu. Aku menyaksikan peperangan yang mungkin tidak pernah terjadi atau mungkin memang pasti terjadi.
Dari tempatku, aku mendengar pekik sedih, jerit kematian dan teriakan-teriakan seperti perintah untuk membunuh atau membinasakan. Selintas pikiran menyatakan bahwa itu adalah tanda bahaya. Aku menyaksikan tiga orang sedang berdiri di puncak bukit tandus. Seorang mengayunkan senjata berulang-ulang di udara. Seorang yang lain meniupkan terompet dengan bunyi yang lebih mirip dengung kematian. Seorang lagi berjalan menghampiri tunggangan yang berbalut kain berwarna kelam lalu berkuda menuruni sisi lereng yang curam.
Dari tempatku, aku berpaling pada arah yang lain. Aku memusatkan pandangan pada dataran yang lebih rendah. Aku melihat ayahku, Rakai Panangkaran, sedang mengangkat sebilah logam yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Benda itu, mungkinkah itu adalah keris yang terkenal dengan sebutan Mpu Tantri Gayatri? Dari bagian atas benda tajam itu tampak darah yang menetes dari tempat yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sedang tergelar pertunjukkan apakah? Aku tidak dapat mengerti karena tetesan darah itu tiba-tiba muncul dari angkasa dan hanya jatuh tepat di atas benda berliau yang dipegang ayahku.
Dari tempatku, aku melihat suasana berubah menjadi suram. Matahari yang sedang menanjak langit dari sebelah timur tiba-tiba terlihat keruh. Kabut dan mendung berayun-ayun lembut lalu memayungi segenap yang ada di permukaan padang.
Aku merasakan ketegangan. Aku merasakan kengerian. Aku merasa bahwa kebinasaan akan terjadi, meluas lalu menyeret banyak orang pada api peperangan yang telah menyala. Aku mengangkat wajah ketika sebagian diriku ingin mendaki puncak yang tertutup mata.
“Sang Hyang,” sapa lembut seseorang dari sisi kanan.
Pada saat aku mendengarnya, aku rasa harus segera pulang dari pengembaraan yang sedang berlangsung di tempat dan waktu yang lain. Aku memanggil serpihan-serpihan jiwaku agar cepat menggabungkan diri di istana yang disiapkan untukku.
“Aku datang,” jawabku dalam hati.
Aku membuka mata lalu memandang wajah dayang yang bersimpuh di bawah kakiku. “Lihat dan tataplah wajahku,” perintahku padanya.
Dia menengadah.
Aku melihat kesedihan yang sedang mengganjal hatinya. “Adakah sesuatu yang perlu aku lakukan pada malam ini?”
Dia mengangguk. Sorot matanya menyatakan rasa dan pikiran yang masih rapat tersimpan dalam hatinya. “Saya melihat rembulan muda yang malu-malu berlindung di balik punggung bukit,” katanya lirih.
Aku tersenyum mengerti maksudnya. “Baiklah, mari bersegera.”
Aku bangkit, melangkah menuju ruang makan yang bersebelahan dengan altar pemujaan. Dayang perempuan yang patuh, pikirku sewaktu menangkap pergerakannya yang mengikuti kibas lenganku ketika mengajaknya beranjak.