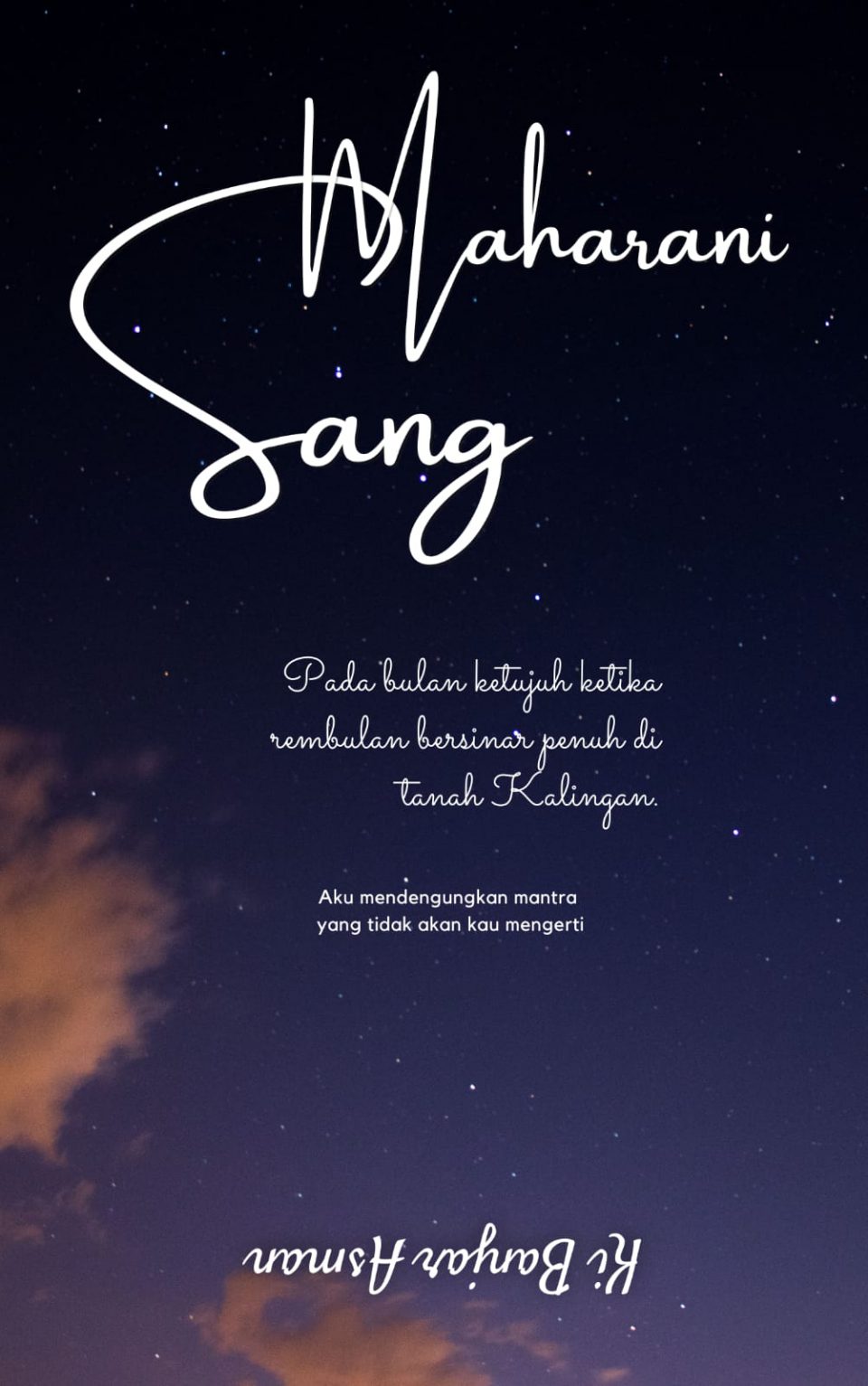Aku kembali mendengar suara Rakai Panangkaran merambat di dalam ruangan. Katanya, “Kebanyakan orang menunjuk kegagalan yang dilakukan pendahuluku sebagai kelemahanku yang memalukan. Tudingan itu kerap ditujukan padaku. Sedangkan penyebab kegagalan yang terjadi adalah orang-orang lebih banyak berbicara mengenai segala sesuatu yang tidak penting. Karena itu, aku akan penuhi sumpah pada ayahku, pada dewa-dewa dan semesta akan mengitariku sebagai satu-satuya sumber kekuasaan.”
Sunyi melanda segenap isi ruangan seperti banjir bandang yang pernah melanda Kalingan ketika ayahku berhenti mengucap kata.
“Aku tidak ingin mengingkari kebenaran. Aku katakan bahwa sebagian ucapan dan tudingan mereka adalah kebenaran. Sebagian orang berkata dengan nada-nada yang cukup gila untuk didengar tetapi mereka benar. Sebagian lagi menuturkan ucapan-ucapan yang mempesona jiwa-jiwa yang kering kerontang agar mendapatkan pujian dan imbalan yang pantas menurut timbangan mereka, tetapi mereka terjebak dalam pusaran yang digerakkan oleh keinginan semu,” lanjut Rakai Panangkaran. Beliau kemudian memandangku dengan sinar mata penuh makna. Makna yang sangat sulit tercerabut sebagaimana renda-renda kain pengantin yang mudah putus. Ayahku tersenyum. Aku melihat gambar-gambar indah sedang dilukis tepat di tengah-tengah bola mata beliau. Lalu beliau kembali berkata, “Dyah Murti. Aku mengawali sumpahku dengan membangun candi-candi dan meja-meja persembahan. Bangunan-bangunan itu bukan dibangun tanpa kebencian. Meja-meja akan dipenuhi sesaji yang diulurkan oleh tangan-tangan yang digerakkan oleh kemarahan.”
Aku merenung. Aku tercekat. Bagaimana seorang penyembah dapat membangun negeri dengan amarah? Apakah Rakai Panangkaran adalah Rahwana yang menampilkan wajah yang berbeda? Oh, tentu bukan itu. Aku yakin aku bersalah bila membandingkan ayahku dengan Rahwana. Mereka adalah jiwa dan tubuh yang berbeda, demikian keterangan Han Rudhapaksa padaku setahun silam.
Ibuku berkata kemudian, “Apakah engkau mempunyai bisikan hati yang sulit terucap, Dyah Murti?”
Ah, perempuan hebat itu seperti mendengar suara hatiku. Untuk menjawab pertanyaan itu, tentu bukan hal yang sulit tetapi aku harus tahu diri. Untuk sejenak waktu, aku membutuhkan ruang yang cukup luas untuk berpikir. Aku menempatkan sepasang telapak tanganku di depan dada sebagai tanda agar ayahku memberi kelonggaran padaku.
“Engkau dapatkan itu,” kata Rakai Panangkaran.
Ah, begitu lega. Begitu menyejukkan. Suara ayahku benar-benar seperti udara yang mengisi setiap kantung kehidupan. Aku harus dapat menata hatiku sebelum membuat udara bergetar karena suuara sumbang. Aku tersenyum geli dalam hati ketika membayangkan suaraku yang sumbang akhirnya didengar ayahku.
Baiklah, aku kemudian berkata pada ayahku, “Yang Mulia Maharaja Bhumi Mataram, kakek pernah mengucapkan sesuatu yang sebenarya tidak dapat saya mengerti ketika beliau menerangkan keadaan tertentu.”
“Katakan. Aku membutuhkan keberanian seorang perempuan untuk menyeimbangkan keadaan.”
“Ayah, kakek tidak pernah suka melihatku berbuat sesuatu dengan berlebihan. Setiap kali saya bermain di sungai, maka kakek segera menyusulku meski belum ada pakaian yang basah. Namun beliau tidak mem=nyuruhku pulang. Beliau hanya melihat yang kami perbuat di sungai. Dan begitu seterusnya dalam banyak suasana dan keadaan.”
“Adakah hal yang lain dikatakan beliau pada lain waktu?”
“Benar. Ayah benar bahwa kakek akan menerangkan alasan-alasan.”
“Apakah engkau dapat memahaminya?”
“Tidak. Saya kesulitan untuk memeras setiap sari dari yang beliau utarakan. Tetapi saya dapat mengingat banyak pesan beliau lebih baik daripada saya menghitung jumlah bintang yang berkilau di langit Kalingan.”
“Menarik. Lanjutkan.”
Lantas aku menyalin ucapan-ucapan kakekku di depan ayahku dengan cukup baik. Di bawah kaki Rakai Panangkaran, aku mengatakan ;
bahwa Han Rudhapaksa tidak pernah menyukai kehancuran sebuah tatanan.
bahwa Han Rudhapaksa sering berharap akan lebih banyak orang yang membenciku daripada menyanjungku.
bahwa Han Rudhapaksa meyakini bahwa racun dapat terlihat sebagai obat penawar yang diidamkan oleh banyak dewa dan orang-orang suci.
Rakai Panangkaran melempar senyum pada ibuku, Lis Prabandari, kemudian kata beliau, “Selalu dan selalu seperti itulah ayahmu.” Ibu menanggapi dengan senyuman tetapi senyum itu bermakna cukup dalam bagiku.
“Kurang lebih, seperti itulah yang dapat saya ingat, Ayah,” aku berkata dengan wajah menunduk.
“Dyah Murti,” ucap ayahku kemudian, “berapa banyak orang terhormat dan berusaha menjaga martabat? Itu tidak dapat dihitung oleh tangan. Banyak orang berkedudukan tinggi dengan gagasan dan perbuatan yang hebat, namun, bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan itu? Tak terhitung pula yang meraihnya melalui pengorbanan yang tabu dilakukan. Andai mereka rela menggeser perasaan lebih tinggi, mereka akan malu mengakui masa lalu.”
Aku pikir ayahku berputar-putar terlebih dulu sebelum menyatakan maksud beliau. Atau mungkin aku terlalu jauh berprasangka padanya?
“Itulah sebab kakekmu setia pada jalan pikirannya bahwa setiap perkembangan tidak sepatutnya menghancurkan sesuatu yang sedang berlangsung atau telah berlangsung. Perkembangan tidak selalu harus dituntut untuk menyediakan tumbal. Namun agar engkau tidak salah mengerti, tumbal tidak selalu mempunyai sifat dan watak yang buruk. Tumbal adalah buah dari gagasan, sikap dan perbuatan. Seseorang dapat menjalankan satu atau beberapa kesepakatan untuk menuju satu kepentingan. Meski demikian, agar engkau juga tahu, kesepakatan juga kerap menemui jalan buntu.”
Aku masih berpikir bahwa ayahku tetap berputar-putar sebelum menyatakan tujuan beliau. Atau mungkin aku terlalu jauh berprasangka padanya?
“Dyah Murti. Aku hadirkan engkau di kota ini, di dalam ruangan ini untuk sebuah maksud. Aku mendengar perkembanganmu dan sekarang, aku melihat perkembangan itu,” kata Rakai Panangkaran sebelum berhenti untuk menghela napas. Lanjutnya kemudian, “Tumbal atau pengorbanan. Dyah Murti, apakah engkau percaya bahwa seorang ayah akan rela membunuh anaknya sendiri?”
“Saya banyak mendengar kisah-kisah masa silam dari kakek,” aku berkata, “tentang pengorbanan, tentang keinginan dewa agar kita bersedia membuktikan isi perasaan. Saya banyak mendengar kisah-kisah percintaan lelaki dan perempuan, kisah percintaan yang menurunkan dan yang diturun. Kakek banyak bercerita tentang kesedihan bocah yang kehilangan air susu ibunya. Kakek sering menirukan ratapan-ratapan sedih orang-orang yang patah hati. Namun, saya sudah menyiapkan diri untuk itu semua.”
“Bagaimana ayahmu tahu?” tanya Lis Prabandari.
Aku berpaling, menatap sepasang mata dengan alis yang elok dipandan, lalu aku bersuara, “Penyergapan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Kayu Merang.”
“Apakah itu berarti engkau setuju dengan rencana yang masih berada di dalam pikiran ayah?” Rakai Panangkaran bertanya.
“Apabila Kayu Merang membenci saya, niscaya dia tidak akan mengirim orang untuk menyerang kami,” jawabku. Oh, aku baru mengerti : ini adalah yang dimaksud kakekku bahwa dibenci dapat menjadi salah sebab niat jahat menjauh dariku. Menjadi yang tersanjung? Mungkin itu juga awal dari bencana. Baik, baiklah, walau terlalu dini menyimpulkan itu, tetapi masih lebih baik daripada aku biarkan benakku berisi kekosongan.
“Apakah itu mempunyai makna bahwa engkau dapat menerima Kayu Merang sebagai pendampingmu?” Rakai Panangkaran bertanya.

“Ayah, mungkinkah kebencian dapat menjadi api dapat memberi kehangatan abadi di dalam ruang tengah sebuah rumah?”
“Seorang istri dapat menghancurkan. Seorang istri pula dapat menjadi pilar kejayaan. Seorang istri pula dapat menjadi persembahan,” jawab Rakai Panangkaran.
Ibuku menambahkan, “Seorang istri dapat menjadi dewa sesembahan.”
“Bagaimana saya dapat mengerti inti ucapan Anda berdua? Ayah? Ibu?” Aku memandang wajah Rakai Panangkaran dan Lis Prabandari bergantian. Pikirku, ini adalah hubungan suci. Hubungan yang dapat memberi warna. Ya, warna bernoda atau warna bernuansa dewa. Apakah aku dapat menerima kedudukan sebagai istri yang disembah? Mungkin, mungkin ini yang dapat terjadi padaku bila aku menerima pinangan Kayu Merang.