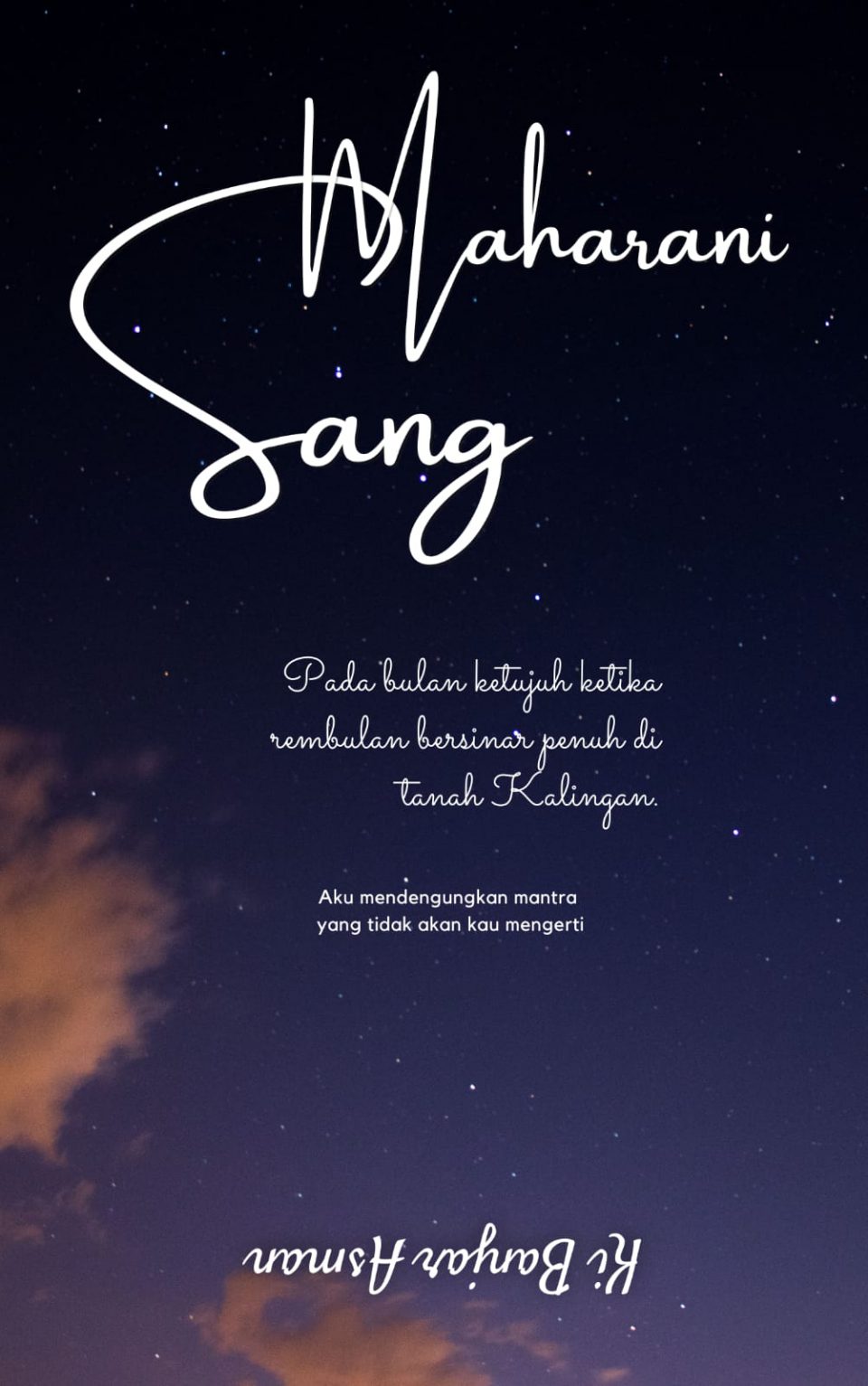“Seorang istri mempunyai ruang dan waktu untuk tidak mencampuri urusan suaminya. Namun, kadang-kadang seorang istri dapat terlalu jauh mengendalikan suaminya. Dyah Murti, penyebab atau sesuatu yang dianggap sebab dapat muncul di luar kehendak dan kemauan seseorang,” kata Rakai Panangkaran sambil mengerling pada Lis Prabandari. Kemudian beliau meneruskan, “Ibumu memenuhi janji padaku dengan tidak menempatkan dirinya pada segala pekerjaanku. Tetapi aku mempunyai permintaan yang lain padamu, sekarang.”
Ibuku mengangguk sambil tersenyum padaku.
Rakai Panangkaran menepuk tangan sekali, sekejap berikutnya, muncul dua perempuan yang mungkin seusia denganku. Mereka cantik dan bertubuh semampai. Mereka berpakaian ringkas, aku pikir itu lebih mirip dengan yang dikenakan oleh para lelaki. Ayahku kemudian menerangkan bahwa mereka berdua akan menjadi senjata pengapit yang lekat denganku. Pada setiap penjuru yang aku tuju, mereka akan menyertaiku, demikian penjelasan ayah padaku. Mungkinkah gerak gerik dan sepak terjang mereka terikat dengan sumpah seperti ayahku mengikatkan diri pada kalimat-kalimat suci? Entahlah. Aku ingin mengembara dalam angan-anganku supaya dapat lebih jauh mengenal dua perempuan itu.
“Anindita Rukmi,” ucap salah seorang dari mereka ketika menyebutkan nama.
Senyumku mengembang sewaktu aku memandang Anindita. Berdagu sedikit lancip. Rahang yang cukup lembut untuk ukuran pengawal yang kerap berolah kanuragan dengan keras. Sepasang matanya begitu indah dengan alis yang lentik. Bersanggul pendek dengan konde yang cukup tersembunyi.
“”Gita Nirvati,” kata seorang lagi. Mengenakan pakaian ringkas dengan kain kaku yang menutup sebagian lehernya. Ah, leher yang indah. Jenjang dan mulus. Ayahku dikelilingi dewi-dewi bermata jelita. Ayahku terlindungi oleh sutra-sutra yang berdarah dingin. Aih, mereka adalah senjata yang mematikan. Pikiranku berkelana liar. Aku lupa bahwa sebenarnya aku pun harus membalas perkenalan Gita Nirvati.
“Dyah Murti,” ucap ibuku dengan lirih.
“Mungkin saya lupa bahwa saya masih berada di tempat ini,” kataku sambil tersenyum malu.
Rakai Panangkaran memandangku dengan sorot mata yang telah berubah. Lebih tajam. Lebih tegas. Dan aku merasakan seperti dipeluk oleh wibawa yang luar biasa. Lututku bergetar ketika aku mencoba membalas pandang mata ayahku. Aku berkeringat. Apa yang sedang terjadi padaku? Ini, suasan ini mengingatkanku pada malam perendaman ketika purnama di Kalingan. Serupa meski tak sama. Tidak terlihat meski nyata.
Terdengar derap langkah mendekati tempat kami berada. Seorang lelaki muda berjalan dengan dada tegap lalu merendahkan tubuh saat berjarak enam belas langkah dari Rakai Panangkaran. Sekejap kemudian, lelaki muda itu berdiri, berpaling padaku kemudian berkata, “Ra Gawa.”
Bukan tampang yang buruk bila aku berkhayal dapat bersanding dengannya. Mungkin Ra Gawa lebih rupawan dibandingkan wajah Poh Sangkhara yang belum pernah aku lihat. Namun, bisa jadi, justru Kayu Merang adalah lelaki paling tampan di antara mereka bertiga. Seorang lelaki sedang aku saksikan sepenuhnya, dua lainnya? Belum pernah aku temui. Bagaimana aku dapat membandingkan keadaan mereka bertiga? Aku tertawa dalam hati dengan segala angan yang cukup gila ini.
“Saya belum lama keluar dari bilik yang pekat dan gelap. Untuk beberapa waktu, saya benar-benar belum dapat menyadari perkembangan dari waktu ke waktu semenjak duduk di ruang ini,” ucapku setelah menerima uluk sapa Ra Gawa.
Barangkali ini yang pernah dikhawatirkan oleh Han Rudhapaksa.
Aku mengalami kejutan-kejutan dari segala perubahan perilaku, tatanan, kebiasaan dan sebagainya.
Aku adalah seorang gadis yang masih berdada tipis.
Aku adalah seorang dara yang belum mempunyai banyak bulu di kemaluan.
Aku adalah perempuan yang sering mengalihkan wajah bila berpapasan dengan lelaki.
Sekarang, segalanya berubah.
Aku dapat melihat lelaki lebih lama daripada di Kalingan.
Aku mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan mereka berbuat sesuatu, termasuk jika aku ingin melihat mereka telanjang seperti bulan yang tiada pernah berpakaian.
Aku dapat menyuruh seseorang untuk membunuh dirinya sendiri.
Dan aku adalah putri Rakai Panangkaran yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Bhumi Mataram.
Bukankah itu mengejutkan?
Aku berada di dalam kesadaran penuh. Aku tumbuh sebagai seorang prajurit, demikian Han Rudhapaksa mengajarku. Hal yang tidak aku ketahui sebelumnya, prajurit. Mungkin ada perihal lain yang belum atau tidak diungkapkan oleh kakekku. Aku pejamkan mata,membayangkan yang sedang dilakukan kakekku. Memikirkanku? Merenung di sisi pematang sawah? Wajah Han Rudhapaksa tergambar nyata dalam benakku dengan segala keperkasaan yang ada di dalam dirinya. Han Rudhapaksa, renta dan dipenuhi kehormatan. Aku harap, aku dapat kembali ke dalam pelukan beliau yang sehangat mentari pagi.
Aku berada di dalam kesadaran penuh. Musim akan berganti. Musim tanam akan berganti musim panen lalu jalan-jalan akan dipenuhi suara-suara yang menggema dengan bahagia. Kemudian derai bahagia akan luruh lalu digantikan musim kemarau. Kemarau, sebagian orang menganggapnya sebagai musibah. Sumur-sumur tiada mampu menyusui ternak-ternak yang berkulit kering. Sungai-sungai di Mataram akan menyusut kemudian bocah-bocah menangis seperti bayi yang terpisah dari payudara ibunya yang penuh berisi susu. Penguasa semesta akan menggulung tirai kemarau panjang lalu menurunkan air dari celah-celah awan yang bergelantungan tanpa lengan. Bocah-bocah mungkin tak lagi menangis. Kesedihan mereka direnggut oleh orang-orang dewasa yang berjuang keras menahan air yang tumpah.
Aku berada di dalam kesadaran penuh lalu aku putuskan untuk menghentikan bayangan sebelum segalanya berubah menjadi mengerikan.
Di bawah dekap mata Rakai Panangkaran, aku dapat mendengar dentum jantungku yang belum berhenti bergetar. Memaksakan diri, ya, aku harus memaksa, aku harus melawan, aku harus dapat memandang wajah dan bertatap mata langsung dengan ayahku, Rakai Panangkaran.
Aku menggigil.
Aku paksakan bibirku agar mau mengucapkan kata-kata. “Apakah tanaman tetap bersemi meski saya teraih oleh kehangatan Kayu Merang?”
“Mungkinkah aku menjawabmu dengan pertanyaan?”
“Saya belum dapat meyakinkan diri untuk sebuah pertanyaan, Ayah.”
“Apabila engkau berpikir tentang kehangatan dan kebahagiaan di Jatiraga, bukankah engkau juga telah mengulurkan tangan pada prahara?”
“Dapatkah prahara dan sinar mentari bersatu?”
“Sinar mentari adalah prahara apabila engkau merasa bahwa hidupmu adalah sebuah persembahan dari ayah untuk penguasa semesta.”
Aku menggigil.
Lis Prabandari beralih tempat. Beliau duduk di sampingku. Sebelah tangan membelaiku. Aku terlelap. Kekacauan pikiranku mendadak lenyap. Benakku berisi ruang-ruang yang sangat senyap. Perasaanku penuh dengan pecahan-pecahan gambar yang terbengkalai.
Aku menggigil.
“Dyah Murti,” kata ayahku, “sumpahku dipenuhi dengan timbangan-timbangan yang menuntut keadilan. Sumpahku berisi ikatan-ikatan keluarga semua orang di Mataram. Sumpahku juga mengikat kebiasaan lama yang berlaku di negeri ini. Sumpahku dipenuhi dengan kebencian serta kemarahan pada setiap pelanggaran kehendak penguasa alam.
“Dyah Murti. Anindita Rukmi, Gita Nervati dan Ra Gawa akan memapahmu. Mereka akan menjelaskan padamu di ruang yang terpisah.”
Aku mengerat rahang yang berderak. Aku pikir, lebih baik berpisah dengan Rakai Panangkaran untuk sementara waktu. Aku harus membebaskan suasana jiwaku yang terkungkung oleh keagungan martabat seorang raja. Aku tidak ingin mati dengan jantung yang terputus oleh ucapan ayahku sendiri.