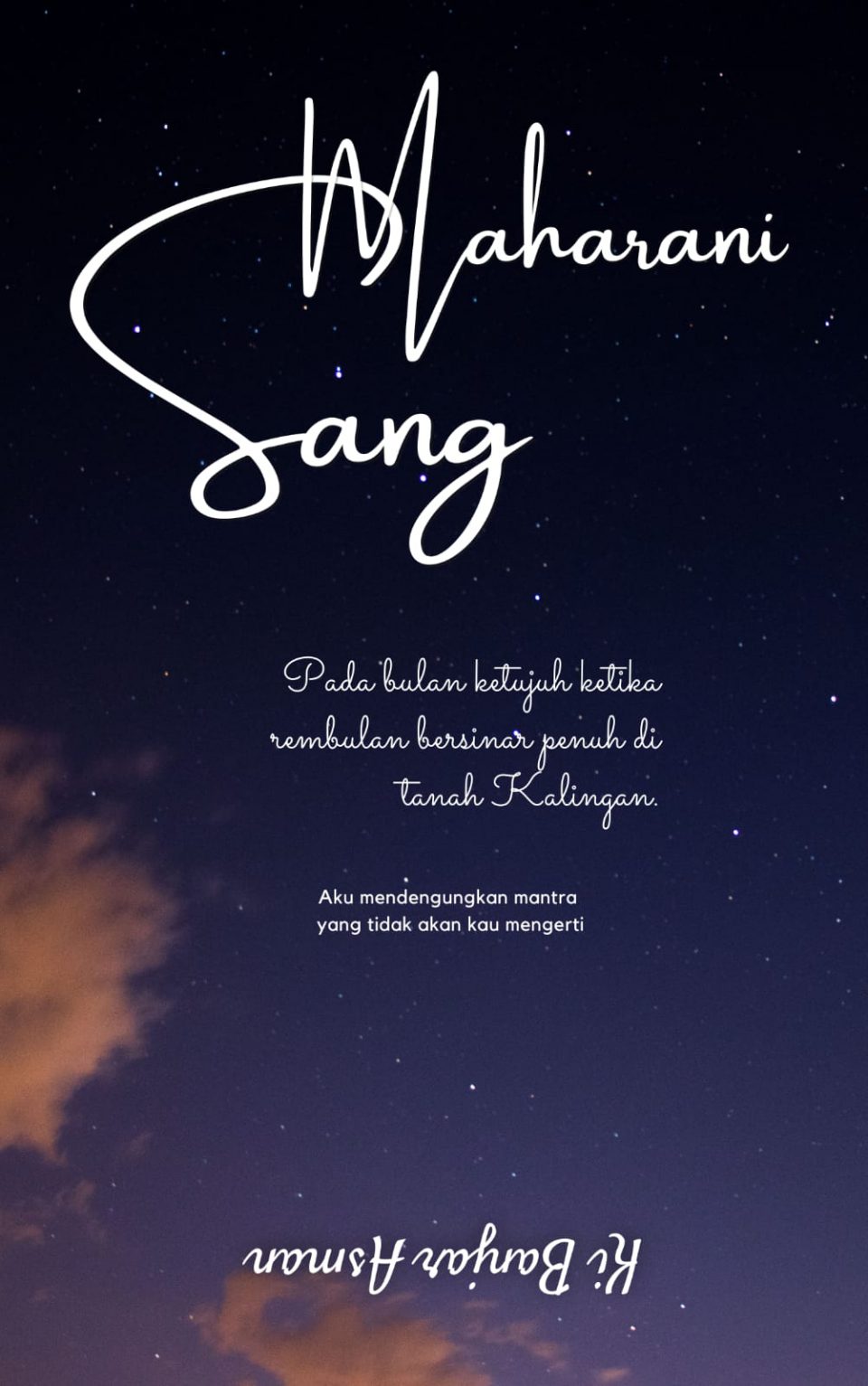Setelah peristiwa aneh itu berlalu, aku dapat bernapas lega meski keterkejutan belum sepenuhnya melepaskan diri dariku. Aku ingin mengungkapkan sesuatu. “Sekarang, serangan kedua mereka justru membinasakan mereka sendiri,” aku berkata, “kematian beberapa orang akan menjadi bahan pertimbangan mereka untuk langkah selanjutnya.” Pada titik itu, dengan nada bicara yang belum pernah aku nyatakan, aku merasa bahwa yang sedang bicara dan berpikir bukanlah diriku sendiri. Bukan Dyah Murti Hansa Gurunwangi, tetapi sebuah kekuatan rahasia, kekuatan asing yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Baik Anindita Rukmi dan Wong Awulung sepertinya menyadari perubahan yang terjadi padaku. Aku dapat merasakan itu melalui cara mereka memandangku. Ketika pandang mata kami berbenturan, aku dapat melihat para prajurit Rakai Panangkaran berada di punggung-punggung kuda mereka, berpacu cepat menuju pada sebuah lembah yang luas dengan sedikit pepohonan. Mereka mengayunkan pedang, tombak dan banyak senjata yang memancarkan sinar kematian. Aku dapat merasakan suasana yang terjadi di balik dua pasang mata pengiringku. Benar, para prajurit Mataram telah dilontarkan dari wilayah samar ke sebuah tempat yang dipenuhi orang-orang mati.
Pada wajah Anindita Rukmi, aku dapat merasakan bawah perempuan muda itu menyimpan rasa takut. Apakah dia takut padakau atau yang lain? Entahlah, meski sebenarnya aku ingin menanyakan itu padanya tetapi keadaan tidak memberi dukungan padaku. Lantas, aku berpaling pada Wong Awulung sambil bertanya, “Apakah kita tidak menunggu hingga malam untuk memindahkan mayat yang banyak seperti ini?” Telunjukku mengarah pada tempat para pelayan yang sedang membersihkan dan membenahi bekas perkelahian.
“Atas keperluan apakah?” Wong Awulung balik bertanya padaku.
“Agar tidak berkembang menjadi percakapan liar di antara banyak orang di pasar dan di jalanan,” jawabku.
“Itu sama saja, Sang Hyang,” ucap Wong Awulung. “Orang-orang akan tetap membicarakan peristiwa yang berlangsung di tempat ini meski kita telah menutup rapat dari telinga dan mata kebanyakan orang.”
Aku picingkan mata. Pikirku, pendapat Wong Awulung memang benar. Dia cukup meyakinkan dengan nada suara dan bahasa tubuh yang sangat tegas. Penyerangan atas asrama keputrian atau tepatnya istana yang dikhususkan untukku dapat dinilai sebagai sayatan tipis pada wajah ayahku, Rakai Panangkaran. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa itu adalah pemilihan tempat yang bodoh untuk bunuh diri. Bisa jadi, pengatur serangan sudah memperhitungkan segala sesuatunya dengan sangat rinci dan berhati-hati tetapi yang dihadapinya adalah Gita Nervati.
“Dari mana mereka tahu, Paman?” aku bertanya pada Wong Awulung.
“Kita tidak dapat mengekang percakapan yang terjadi antara suami dan istri atau bapak dengan anak. Itu adalah percakapan rahasia, walau setelahnya, mereka dapat menebarkan isi pembicaraan di keramaian.”
“Kita tidak dapat mengekang,” desisku mengulang. “Baiklah, Paman harus melarang setiap orang yang berada di dalam tempat ini untuk keluar atau pulang. Kita dapat menanti sampai besok malam, lalu diam-diam menyamarkan mayat sebelum membuat perapian untuk mereka di sisi hutan sebelah utara.”
Kitab Kiai Gringsing : Geger Alas Krapyak
“Anakku,” ucap Wong Awulung. “Pada segala arah ketika kita berpaling, yang terlihat adalah tulang punggung yang patah atau yang sudah terbungkuk. Itu adalah keadaan yang sudah tidak sejalan dengan kawah Merapi yang setiap hari bergolak tak terputus. Apa artinya? Saya bicara tentang orang-orang yang dipenuhi dendam. Mereka telah berpatah tangan dan leher pada malam ini, mungkin besok atau lebih cepat lagi, mereka akan kembali demi sebuah penuntasan. Dan sepanjang waktu itu ketika para pelayan dan penjaga bermalam, apakah mereka pun akan kita seret pada pertempuran?”
“Benar,” aku berkata datar. “Tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan gelanggang perang. Istana ini akan menjadi medan perang, Paman harus siapkan segalanya. Keputrian ini harus diubah menjadi neraka sesuai kemampuan dan keinginan para pelayan dan penjaga.” Aku berpaling pada Gita Nervati meski tak perlu menunggu persetujuannya, tapi aku kira perlu memandang wajahnya.
Lingkungan pun sepi ketika kami membubarkan diri. Sejurus waktu berlalu, Wong Awulung berkata padaku sewaktu kami duduk berhadapan di serambi istana keputrian, “Karena tidak ada seorang pun yang diperbolehkan meninggalkan keputrian, maka ada sesuatu yang harus dikerjakan jika mereka datang dengan jumlah lebih banyak dari pada serangan sebelumnya.”
“Demikianlah yang akan menjadi tanggung jawab orang tua yang bernama Wong Awulung,” aku berkata dengan senyum mengembang. Aku merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang menjelang. Selagi Wong Awulung berbicara mengenai siasat yang mungkin dapat diterapkan bila ada serangan susulan, Gita NervatI tampak berjalan mendekati pada kami. Aku melihatnya berhenti sejenak. Mungkin dia merasa kurang sopan bila bergabung dengan kami berdua. Aku pikir perlulah untuk memanggilnya. Sebuah pembahasan akan menjadi bertambah bobot jika Gita Nervati berada di tengah kami.