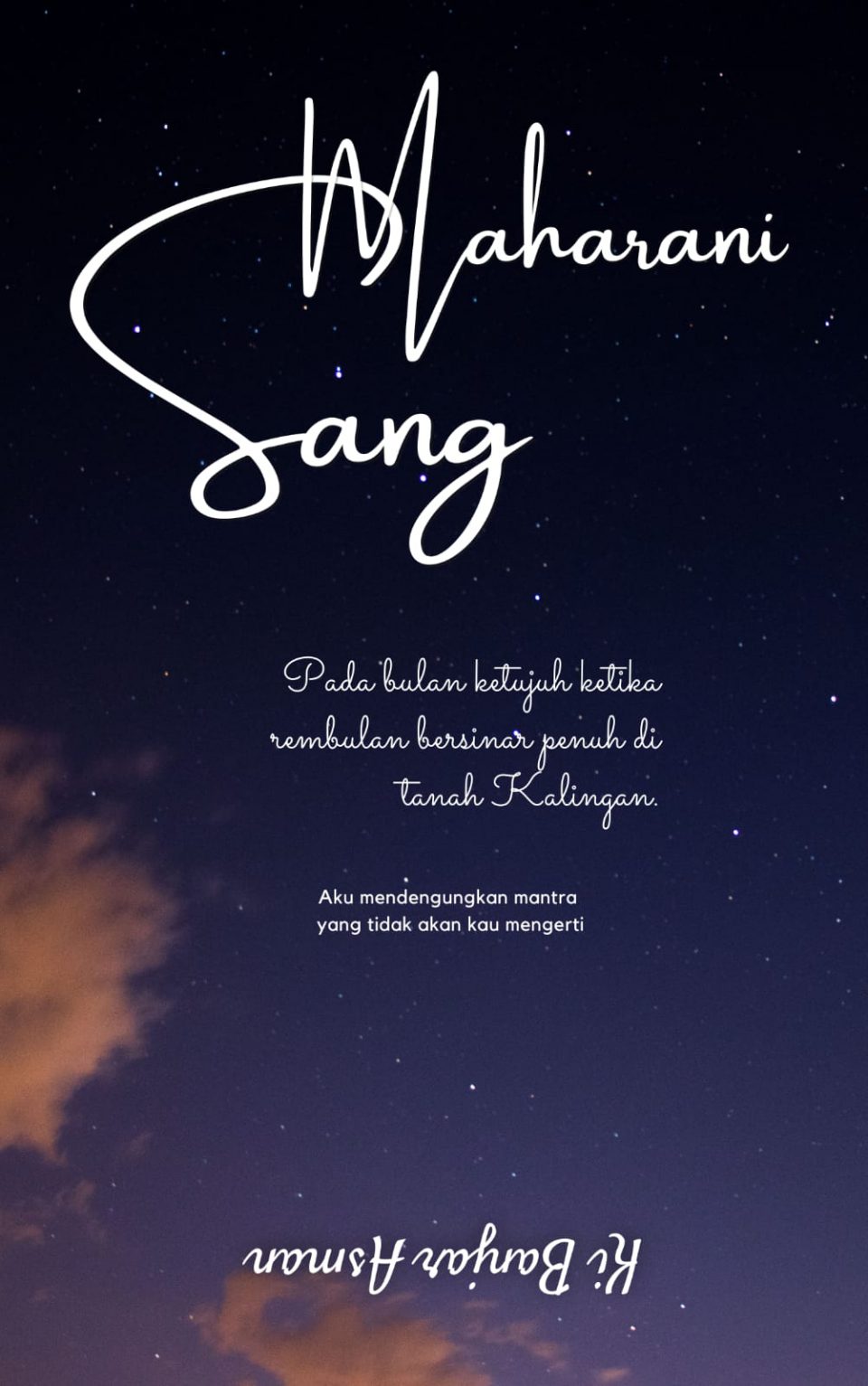Aku tidak dapat melihat Gita Nervati dan Wong Awulung. Seandainya wajah mereka memperlihatkan perubahan, aku tidak akan tahu.
“Apa artinya, Sang Hyang?” Wong Awulung bertanya padaku.
Aku tidak ingin membesarkan kepala meski nada suara Wong Awulung menggetarkan keheranan. Buat apa? Bukankah pertanyaan Wong Awulung sudah menyiratkan keingintahuan dan penasaran, lalu buat apa aku harus besar kepala? Jujur, aku ingin membuka mata tetapi aku tak kuasa. Aku ingin meronta dari kegelapan yang membungkus penglihatanku kemudian menoleh sekitar, sekali lagi, aku tidak berdaya. Kemudian, aku bersuara sebagai jawaban atas pertanyaan itu, “Aku melihat padang rumput yang berbukit-bukit. Bukan barisan bukit yang besar tapi lebih menyerupai belasan atau puluhan tanah bergunduk setinggi atap rumah atau lebih. Padang yang menghampar luas dengan sedikit rimbunan semak di atasnya. Padang yang hijau dan sejuk dipandang mata.”
Tiba-tiba aku mampu membuka mata. Wajah Gita Nervati mengerut, demikian pula Wong Awulung. Sedikit jauh, dari balik dinding istana, kepulan asap membumbung tipis kemudian berpendari seakan menjadi tirai bagi sinar rembulan yang malu-malu menyapa permukaan tanah.
“Sang Hyang,” ucap Gita Nervati, “padang yang hijau akan menjadi pertanda baik. Saya berpikir semacam itu lalu berharap dapat meyakininya.”
Aku berpaling pada Wong Awulung yang belum mengucapkan sesuatu. Ah, sepertinya lelaki tua ini sedang menahan pertanyaan atau pernyataan. Mungkin merasa aku memandanginya cukup lama, Wong Awulung kemudian berkata, “Bisa seperti itu, Panglima.”
“Dan bisa juga?” Gita Nervati menggantung pertanyaan.
“Padang rumput itu akan menjadi tanah pekuburan yang lapang bagi kita,” jawab Wong Awulung. “Itu, maksud saya, tanpa persiapan maupun siasat yang memadai, kepergian kita akan sama dengan bunuh diri. Jumlah pasukan tidak selalu menjamin kemenangan. Dan kehebatan siasat pun tidak selalu dapat mengalahkan lawan.”
“Lantas?” aku bertanya pendek.
“Kita memang harus mempunyai rencana dan untuk keperluan itu, Sang Hyang telah menghadirkan Panglima Gita Nervati yang telah duduk bersama kita,” kata Wong Awulung dengan nada tegas dan penuh kepastian.
Aku adalah Dyah Murti Hansa Gurunwangi. Perempuan muda yang pernah berendam pada purnama ketujuh setiap tahun genap. Aku tidak dapat menunggu malam berganti siang, lalu kembali kepada pelukan malam untuk membuat sebuah keputusan. Aku dapat meminta Gita Nervati membuat persiapan secara diam-diam. “Itu benar karena kita belum mengetahui secara pasti jati diri para penyerang. Adalah kebodohan apabila kita meminta ayahku, Rakai Panangkaran, untuk memperketat penjagaan ataupun melakukan pemeriksaan bagi para pendatang,” aku berkata sambil menatap lekat wajah murung Wong Awulung. Sesaat kemudian, aku berpaling pada Gita Nervati lalu berucap, “Kita belum dapat menentukan jurusan atau arah pencarian. Katakan yang kau pikirkan.”
“Saya pikir, sebaiknya kita pergi menyelidiki daerah yang diduga oleh Paman Wong Awulung,” ucap Gita Nervati kemudian mengurai rencana yang tersusun di benaknya secara jelas dan benderang.
Ada kesan bahwa Gita Nervati cukup berhati-hati dalam menyampaikan isi pikirannya. Dia memang harus berhati-hati karena Wong Awulung mengingatkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada kebocoran pada lingkaran dekat Rakai Panangkaran. Tahapan demi tahapan terinci secara jelas dan semakin mendekatkan mereka pada sasaran.
Malam menjauh garis senja ketiak burung-burung gagak terbang sambil melantangkan suara parau. Setitik demi setitik gerimis turun membasahi jalan-jalan dan lorong ibukota Mataram. Gita Nervati telah memungkasi rencananya dan aku sepakat bahwa peninjauan rencana harus selesai sebelum kain-kain basah mengering pada esok hari.
Pertemuan pun selesai.
Goita Nervati mengambil jurusan yang berbeda dengan Wong Awulung. Aku meminta mereka supaya meninggalkanku seorang diri di beranda. Kali ini, aku mencoba menghimpun kekuatan-kekuatan yang pernah aku rasakan semenjak Dewi Rengganis menjumpaiku di Kalingan.
Ada sentuhan yang lebih dingin daripada udara di sekitarku. Ada hembusan panas dari napas yang menyusur keluar dari penciumanku. Sesuatu, ya mungkin lebih tepat disebut sebagai sesuatu, sedang memelukku. Aku tidak dapat menyebutnya sebagai tempelan karena sesuatu yang asing seolah datang alalu membungkusku di dalam kekuatannya. Aku tidak dapat menyebutnya sebagai tempelan karena kekuatan itu berasal dari dalam tubuhku. Aku dapat merasakan sepasang lenganku sedang mengeras. Aku mencubitnya, ah, ini seperti dinding batu yang menjadi penyusun candi.
“Apakah aku harus mencurigainya?” aku bertanya pada sebagian diriku yang bersemayam di dalam relung hatiku.
“Apakah harus begitu?” dia balik bertanya supaya mendapatkan penegasan dariku.
“Yah, sebaiknya memang aku harus mendahulukan sebuah kecurigaan agar tetap waspada dari segala yang tersembunyi dari pandangan mata,” jawabku.