Matahari terus menapak semakin tinggi. Kabut telah beranjak dan angkasa begitu cerah pada siang itu. Aku duduk berdua dengan ibuku di beranda. Beliau terlihat sangat cantik. Giginya berkilau dan sepertinya usia ibu lebih muda dariku. Dengan dua kaki dirapatkan, sikap ibu benar-benar agung. “Pantas bila ibu mendapat tempat di hati ayah,” gumamku dalam hati ketika mengingat penuturan para pelayan yang bekerja di rumahku.
Kami belum banyak bercakap tentang perkara-perkara penting. Ibu lebih banyak mendengar pengalaman berendam saat purnama yang aku anggap sangat janggal. Beliau sering mengembangkan senyum apabila aku merajuk bila keterangan ibu tidak memuaskan hasratku. Di beranda, kami bicara tentang dinding batu yang menjadi pagar halaman kami yang telah diitumbuhi lumut. Kami bertukar kata tentang pohon yang mulai mengering. Aku menyalahkan pelayanku lelaki yang bertubuh kecil. Ia lebih sering menunda pekerjaan dengan kalimat yang sangat membosankan. ‘Nanti pasti aku kerjakan’, kata-kata itu terdengar seperti suara pohon tumbang menurutku. Namun aku selalu membiarkan bila ia abai dengan tugasnya. Biarlah, ia berusia lebih muda dariku. Tunglai adalah namanya ketika ibu memperkenalkan kami.
Sayup-sayup kami mendengar derap kuda yang semakin lama semakin jelas terdengar. Kami dapat melihat dua penunggang kuda yang berpacu dengan debu tipis mengikuti mereka. Rumah kami tidak terletak tepat di simpang tiga, tetapi kami dapat memandang leluasa karena beranda kami sedikit lebih tinggi dan menghadap jalan masuk utama wanua.
Seorang penjaga rumah keluar menunggu kedatangan dua orang pendatang itu di gerbang halaman. Ia berseru sambil melambaikan tangan agar dua penunggang kuda itu mengurangi laju.
Seorang dari mereka melompat turun sambil membawa gulungan lontar. Aku dapat mendengar ketika ia berkata pada penjaga rumah, “Nama saya Was Tiladung. Saya datang atas perintah Sang Hyang Dyah Pancapana untuk mengantarkan lontar pada Dyah Prabandari.” Aku melihat Was Tiladung membungkukkan badan saat mengulurkan gulungan lontar.
“Beliau tengah menanti Anda,” kata penjaga rumah sambil memberi isyarat agar dua utusan Rakai Panangkaran mengikutinya. Tiga orang itu berjalan beriringan menghampiri kami di beranda.
Aku memperkirakan perjalanan dua utusan itu cukup jauh, meski begitu, mereka dapat mengurus diri dengan baik. Kumal dan lusuh sama sekali jauh dari penampilan mereka. Pakaian keduanya masih rapi dengan tubuh yang juga jauh dari kata lelah. Mereka bersikap sopan dan senantiasa menjaga martabat sebagai duta Rakai Panangkaran. Aku terpesona!
Ibu memberi perhatian cukup pada utusan suaminya. Beliau memberi kesempatan pada mereka untuk beristirahat setelah berkata, “Aku telah membaca lontar itu dan kalian dapat segera kembali ke ibukota. Sang Hyang tidak akan menanyai kalian tentang jawabanku.”
Aku mengikuti ibu melangkah masuk ke dalam rumah. Sementara penjaga rumah menemani dua utusan ayahku dengan hidangan-hidangan yang disajikan oleh pelayan rumah kami. Seperti itulah ibu dan kakekku menjamu tamu-tamu mereka. Walau belum mengenal baik, tetapi setiap orang yang memasuki rumah kami tidak akan merasa asing.
Bilik-bilik telah disiapkan bagi dua utusan ayah. Mereka akan menginap untuk semalam dan penjaga rumah akan siap menemani bila mereka memintanya.
Nyala api mulai bermunculan di sepanjang jalan di Kalingan. Temaram senja telah meminta orang-orang wanua agar bersedia menerangi jalan-jalan dan rumah masing-masing. Dalam waktu itu, ibu berkata padaku, “Aku akan bicarakan pesan ayahmu dengan kakekmu setelah makan malam. Dan selepas utusan ayahmu kembali ke ibukota, ibu akan meminta waktumu lebih banyak.”
Sejenak aku merasa murung dengan tekanan suara ibu pada bagian akhir ucapannya. “Ada apakah? Setiap kali ibu berkata seperti itu maka tidak ada sesuatu yang dapat dianggap remeh.” Namun aku tidak mempunyai keberanian untuk mengeluarkan isi hatiku di depan ibu. Sekali lagi, beliau begitu agung di hadapanku.
Ibu memandangiku cukup lama, lalu beliau bertanya, “Apakah kamu ingin tahu pesan ayahmu?”
Aku menggeleng.
“Benarkah?”
Aku menggeleng.
“Sejak kapan Dyah Murti tiba-tiba mampu mengekang rasa ingin tahu?”
Aku menggeleng.
“Baiklah. Lebih baik kamu menetap dalam keadaan tidak tahu untuk malam ini.”
Aku membelalakkan mata.
“Oh, ya tentu saja. Kamu dapat menemani Was Tiladung dan temannya lalu pengetahuanmu akan bertambah, seperti biasanya.”

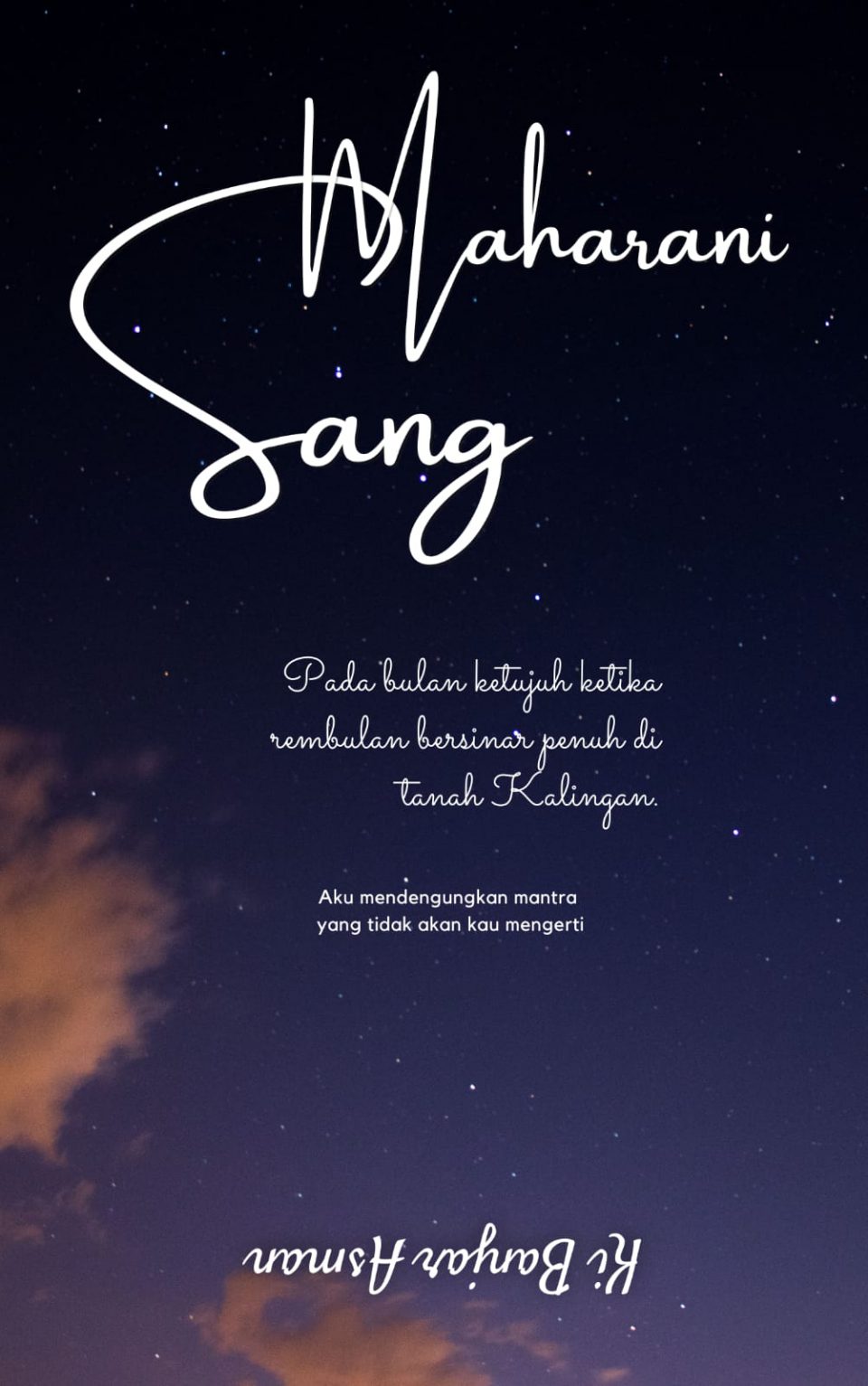
1 comment
[…] Bulan Telanjang 9 […]