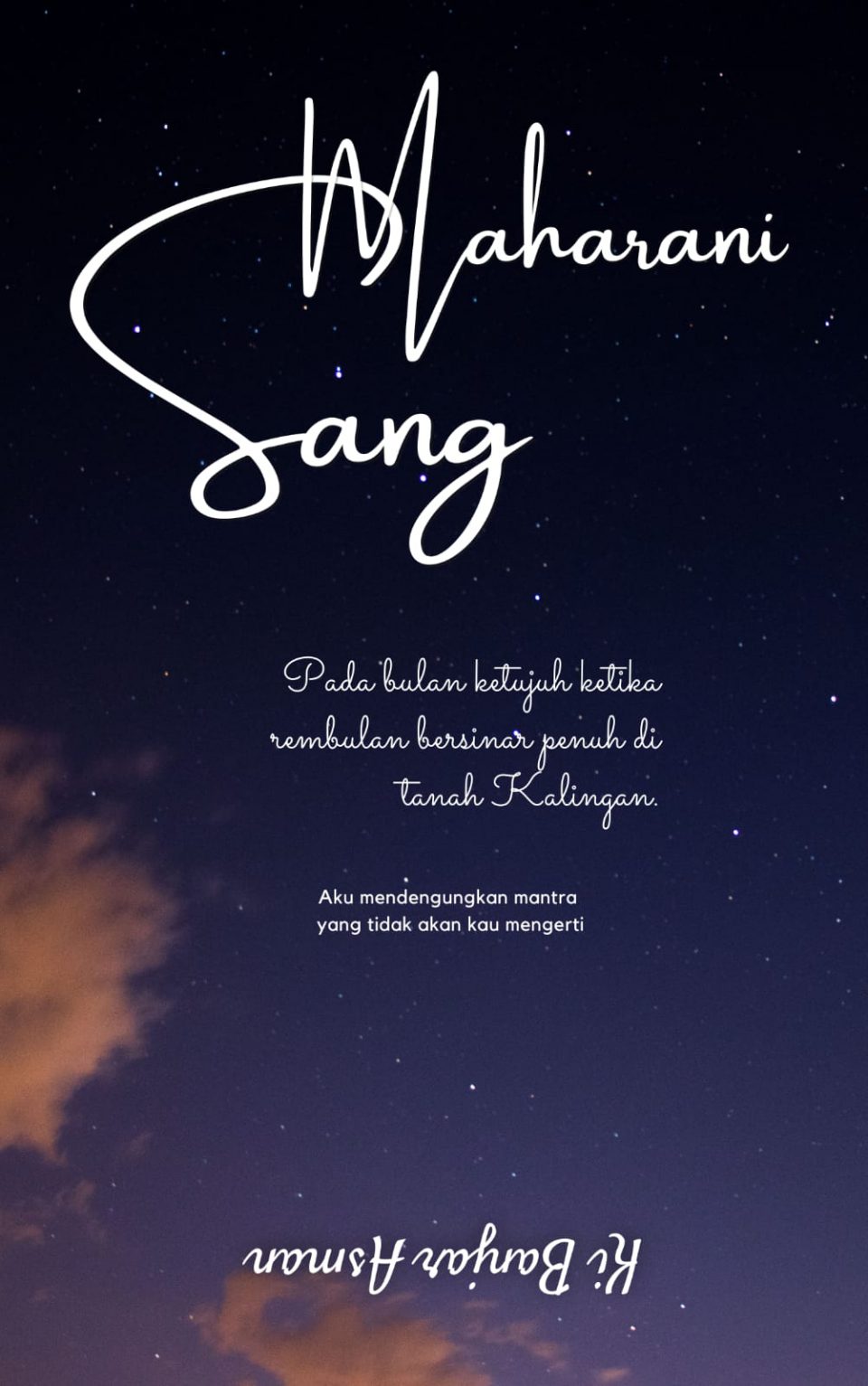“Ini adalah hari yang telah ditentukan bagiku agar menemui dirimu.”
Aku memicingkan mata. Tujuannya sudah pasti bukanlah urusanku, aku pikir seperti itu. Tetapi, dengan bertemu denganku lalu menyatakan maksudnya di depanku, oh, itu akan menjadi bagian dari persoalanku. “Bapak, apakah saya mempunyai kewajiban pada hari ini? Kewajiban yang seharusnya saya penuhi demi kepentingan Bapak?”
“Aku akan menempatkan rasa terima kasih yang sangat besar pada ruang hatiku jika benar kau akan melakukan itu,” kata lelaki berwajah setengah itu, “hanya saja, hari ini bukanlah kewajibanmu untuk menjadi pengganti janji ayahmu.”
Aku, Dyah Murti, benar-benar tidak mengerti arah dan maksud dari segala yang diucapkannya. Bahkan, lelaki ini belum menyebutkan nama sama sekali. Aku dalam kesendirian meski ada bayangan asing yang sedang berbincang denganku, tetapi, bukankah itu tidak kami lakukan di alam nyata? Jemari lelaki itu masih berada di dalam dadaku. Aku dapat merasakan pergerakan tangannya. Aku dapat merasakan ibu jarinya bersentuhan dengan jantungku. Namun aku tidak merasakan kesakitan. Apakah aku harus berduka dalam nestapa karena ajal hampir tiba? Ya, bila ia mau, tentu tangannya dapat bergeser sejengkal lalu meremas jantungku hingga pecah.
Mengapa aku tidak dapat mendengar suara Ra Gawa? Gita Nervati? Anindita Rukmi? Bukankah mereka bertiga adalah pengawal yang berkedudukan paling dekat denganku? Baiklah, aku pikir mereka sedang berkutat dengan kebingungan karena tidak melihatku di depan mata.
Hingga saat ini, aku belum mendengar lelaki itu bernapas atau menggerakkan dada turun dan naik. Ini sebuah keajaiban bagiku! Dia seakan-akan begitu nyata dalam pandanganku meski aku sadar bahwa kesadaranku sedang hanyut oleh getaran halus dari dunia ruh. Dalam keadaan demikian, aku masih dapat mendengar kicau burung-burung liar yang terbang bebas di angkasa luas. Aku tidak sepenuhnya sedang meraga sukma.
Kemudian aku mendengarnya berkata, “Surak Kelurak. Surak Kelurak adalah nama yang aku berikan pada mereka yang bertanya. Setelah mereka mendapatkan jawaban, maka aku akan mendapatkan kepatuhan yang tiada banding. Tetapi, jika kau beranggapan bahwa aku sedang mengejar kedudukan yang sejajar dengan Dewi Tara, maka aku pastikan bahwa anggapanmu salah. Itu pendapat yang sesat.”
“Tentu bukan tanpa alasan atau sebab jika orang-orang mematuhi Anda hanya karena mendengar Anda menyebut nama. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik nama itu. Menurut saya, kepatuhan mereka bukan karena mereka mempunyai ruang yang cukup di dalam pikirannya.”
“Dyah Murti, kau hendak menilai mereka sebagai orang bodoh?”
“Bapak, sesuatu yang tersembunyi akan terungkap sebagaimana matahari menyingkirkan gelap. Perbuatan dan sifat angkara akan tampak begitu terang benderang oleh mereka yang mematuhi Bapak.”
Surak Kelurak memegang jantungku dengan kepalan yang cukup keras. Itu menyakitkan sekali! Dia tertawa lalu wajahnya tampak seperti siluman yang taat pada nilai-nilai kebaikan. Sekejap kemudian ia melepaskan cengkeraman. “Dyah Murti, ucapanmu sangat tajam. Engkau menganggap orang-orang yang mematuhiku sebagai orang yang tidak sanggup berpikir. Engkau pun tegas membandingkan diriku dengan angkara. Anak Rakai Panangkaran, aku katakan padamu, angkara tidak dapat disembunyikan dan pula tidak perlu dirahasiakan dari pandangan mata orang-orang. Sebelum aku pergi meninggalkanmu, ada sebuah pesan yang dapat kau renungkan sepanjang malam. Kebenaran.”
Mendadak kemilau cahaya memenuhi seluruh rongga mataku. Ketika semuanya sirna dalam sekejap, aku dapat melihat Ra Gawa, Gita Nirvati dan Anindita Rukmi masih berdiri di dalam ruanganku. Namun mereka belum berada dalam kesadaran yang sebenarnya. Pandang mata mereka begitu hampa. Raut wajah mereka bagaikan patung-patung yang ditempatkan di sudut-sudut jalan.
Aku menepuk dua tangan. Aku bertepuk tangan berulang-ulang tetapi mereka bertiga bergeming. Mereka bertiga seperti sedang tersumbat pendengaran. Mereka bertiga seakan sedang diterpa kebutaan.
Baiklah, aku ceritakan semua pengalaman sejak memasuki ruangan khusus ini pada mereka bertiga. Barangkali mereka tidak mendengar tetapi, bukankah mereka masih bernapas? Mungkin sesuatu yang samar sedang bergolak dan mengaduk kesadaran mereka. “Ada yang aku tahu dengan pasti semenjak aku meninggalkan Kalingan. Aku perlu kalian semua tahu dan mengerti bahwa kepindahanku ke tempat ini adalah penggenapan sebuah keinginan dan tujuan. Aku yakin kalian juga sudah pasti mendengar bahwa aku sedang berada di bawah pinangan Kayu Merang. Sekarang, aku ingin bertanya, bagaimana jika keadaan itu diterapkan pada kehidupan kalian? Diserahkan pada orang yang tidak dikenal? Dipaksa tunduk pada sesuatu yang dinamakan kejujuran? Aku ingin sekali mendengar suara dan pendapat kalian.”
Penerangan yang ada di dalam ruangan mendadak menjadi suram, dan itu tidak memberiku pandangan yang lebih jelas.
Tiba-tiba Ra Gawa menggerakkan tangan kanan, mengeluarkan sebatang tongkat pendek yang berujung bulan sabit. Ia mengangkat senjatanya tanpa melihat kepadaku, kemudian berkata, “Saya diperintahkan melindungi Sang Hyang dianggap lemah oleh Paduka Rakai Panangkaran. Saya diperintahkan tunduk pada segala keinginan Sang Hyang tanpa ada keadaan yang harus ditukar. Saya, Ra Gawa, menjadi milik Dyah Murti sepenuhnya.”
Keanehan apa lagi yang sedang aku hadapi? Bagaimana Ra Gawa tiba-tiba kembali menjadi manusia sempurna padahal beberapa kedip mata yang lalu, Ra Gawa adalah seonggok daging yang beku?
Meski demikian, aku terpukau oleh kata-katanya. Itu mengingatkanku pada ucapan Surak Kelurak, tunduk tanpa syarat. Hanya kesetiaan dan pengabdian. Aku merasa jiwaku ditarik kemudian dituntun oleh kekuatan gaib yang sulit dimengerti.
Dalam keadaan itu, aku seperti sedang duduk di dalam lukisan kasar yang disiapkan untuk dipahat pada dinding batu yang sedang dirancang Rakai Panangkaran. Aku melihat diriku sedang berhadapan dengan seekor burung yang berekor api. Di bawah sayap burung yang berparuh lengkung nan tajam, aku melihat gambar hidup mengenai peperangan. Burung yang mempunyai lidah api itu memancarkan nestapa pada tatap matanya. Namun, aku hanya dapat menduga-duga ; apakah prahara akan mendatangi kerajaan ayahku?
Waktu terasa lambat ketika melaju, dan burung itu memudarkan wujudnya dalam keremangan yang lebih mirip suasana di dalam gua di kaki bukit sebelah utara Kalingan. Ya, aku terkenang masa silam yang belum berjalan sepuluh tahun ke belakang.
Kesadaran membawaku kembali ke ruangan.
Anindita Rukmi dan Gita Nirvati telah menggenggam senjata basah berdarah sambil menatap tajam padaku. Anindita Rukmi kemudian berkata dengan suara lirih yang ditujukan padaku, “Maaf karena Sang Hyang telah terganggu.” Kemudian ia membalikkan badan , mengayun langkah melewati pintu ruangan lalu memanggil penjaga bangunan.
Toh Kuning adalah pemuda yang menjalani petualangan menggetarkan bersama Ken Arok.
Aku melihat Anindita Rukmi menunjuk sebuah arah sambil berkata-kata dengan cepat tetapi tidak terdengar olehku. Aku melompat mundur, terkejut, ketika melihat seorang lelaki tergeletak di lantai bersimbah darah dengan sebatang pedang melintang di atas dadanya. Lelaki itu telah mati. Mungkinkah ada perkelahian di tempat ini? Terjadi di dekatku dan aku tidak tahu? Rentetan pertanyaan memenuhi lorong-lorong pikiranku.
Desir langkah kaki Gita Nirvati terdengar mendekatiku. “Maafkan kami yang harus mememenggal usaha jahat yang mengancam keselamatan Sang Hyang.” Ia bergeser ke samping, menendang tubuh seorang lagi yang terbaring tidak berdaya. Tapak sepatu Gita Nirvati meninggalkan bekas-bekas berwarna merah darah di wajah orang asing itu dan di atas lantai yang tidak terlihat kotor.
Beberapa penjaga dan pelayan kemudian datang, membersihkan serta membenahi ruangan yang sebenarnya tidak tampak porak poranda.
“Sang Hyang bukanlah seorang tamu bagi kami bertiga,” ucap Ra Gawa sepeninggal pelayan dan penjaga yang menggotong dua mayat yang masih hangat. “Kami hanya menjalankan tugas sambil memastikan agar tidak ada orang yang sembarangan mengambil urusan dengan Sang Hyang.”