“Nyi!” teriak seorang pemuda dari arah kereta yang berada agak jauh dari tempatku. “Kami akan membantu Anda sekuat tenaga!” Ia menyambut terjangan penunggang kuda dengan gerakan yang sangat indah.
Sejujurnya aku tidak mengerti alasan pemuda itu membantu kami, tetapi biarlah, semuanya mengalir tanpa ada campur tangan dari orang-orang yang berada di tanah lapang ini.
Mendadak suara-suara keras saling membentak dan memaki, mendadak udara di tanah lapang beralih menjadi lebih panas dan jemari tangan kebengisan meremas jantung yang masih berdetak. Dari dalam kereta, aku melihat bayang-bayang banyak orang yang bermandi cahaya suram berkelebat dalam perkelahian. Dentang suara beradu makin kerap terdengar dan semakin lama kian menyakitkan telinga.
Aku tidak menilai kepandaian atau ketinggian ilmu kanuragan setiap orang. Mereka serupa dengan dedemit atau sejenis siluman yang kerap dikisahkan Han Rudhapaksa padaku dan pada teman-temanku. Mereka, belasan orang, berkelahi seperti tak menyimpan rasa takut yang tersisa. Aku tidak mengerti jalan pikiran mereka tentang hidup. Bukankah lebih indah bila tidak ada peperangan? Namun itu adalah pendapatku sendiri di tengah kenyataan bahwa masih banyak raja-raja yang berkelahi untuk meluaskan wilayah atau alasan yang lain.
Orang yang bernama Ki Jalapitu menggerakkan senjatanya begitu hebat. Begitu pula ibuku yang mahir memutar selendang berwarna merah. Kapankah Lis Prabandari mengurai selendang? Di mana beliau menyimpannya? Sungguh, aku sama sekali tidak melihat kain panjang itu menempel pada pakaian ibu. Ternyata ibuku benar-benar termasuk perempuan yang pandai menyesuaikan diri. Dua ujung selendang ibuku bergantian membuat suara yang meledak-ledak. Begitu menggetarkan dada. Serangan demi serangan Ki Jalapitu terbendung oleh ujung selendang yang disengaja ibuku untuk melindunginya dari terkaman orang itu. Sementara, ujung yang lain digunakannya untuk menyengat, mematuk dan menghantam simpul-simpul dan cabang peredaran darah. Aku hanya mengira karena aku tidak dapat melihat perkelahian begitu terang dan sejelas burung hantu.
Secara keseluruhan perkelahian masih berlangsung seimbang. Aku tidak dapat menebak pihak yang kalau atau menang. Bagiku, harapan terbesar adalah kami dapat mengalahkan Ki Jalapitu dan pengikutnya. Pertempuran berlangsung sangat cepat. Waktu bergulir seperti sebongkah batu yang terlempar dari tebing tegak lurus. Meluncur deras tanpa penghalang yang sanggup mengurangi kecepatannya.
Harapan tetap menjadi buah yang ditunggu meski kenyataan memberi buah yang berlainan. Begitu pun keadaan kami. Pengawal kami yang dipimpin oleh sais berada di tepi kekalahan.
Aku tidak berdaya menolong mereka.
Aku tidak memiliki kuasa menyeru dewa-dewa agar turun tangan.
Aku pejamkan mata.
Aku bayangkan diriku berpakaian sama dengan ibuku.
Aku bayangkan perempuan berdada besar hadir di sampingku.
Aku bayangkan bahwa aku mempunyai wujud lain yang terlibat dalam pertandingan hidup dan mati belasan orang di tanah lapang.
Dalam bayanganku.
Aku menghadapi seorang penunggang kuda yang bersenjata golok besar dan bertampang halus. Wajah orang ini begitu halus, sehingga sulit dipercaya bila ia terlibat dalam perkelahian untuk memperebutkan seorang gadis, yaitu aku, Dyah Murti.
Dalam bayangan di hati dan benakku, aku berkelahi tanpa senjata. Bukan karena aku tidak mampu tetapi kenyataannya adalah aku tidak menguasai ilmu kanuragan. Dua tanganku berkelebat mengimbangi kecepatan gerak lelaki muda yang menjadi lawanku. Aku mampu menghindari setiap terjangannya yang dapat dipastikan dapat merenggut hidupku. Aku memperbaiki kedudukan dengan gerak kaki yang kerap aku saksikan sewaktu kakekku mengajar ilmu kanuragan pada pemuda-pemuda di Kalingan. Sepasang kakiku membuat langkah aneh tetapi aku tidak sempat memperhatikan bentuk atau mencari guratan-guratan di tanah untuk mencari pola bangun gerak kakiku.
Sesaat lamanya aku terkurung oleh hujan serangan pemuda Jatiraga itu. Tubuhnya ramping dengan sepasang lengan yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang pekerja keras dan ringan tangan. Ah, senang hatiku padanya. Bukan pemalas namun sayang, ia sekarang mengincar kebebasanku!
Aku memutar-mutar tubuh. Aku gerakkan tubuh dalam olah tari yang diajarkan oleh Lis Prabandari. Ternyata penggabungan itu membuatku terlindung di dalam benteng yang tak tampak oleh mata. Selagi aku mulai merasa aman, wajah pemuda itu memancarkan kebingungan yang tidak terlukiskan olehku. Namun aku tidak ingin menebak arah pikirannya. Aku hanya ingin selamat dari serangan gencar pemuda itu.
Mendadak melintas dalam benakku, tiga batang bilah bambu atau sujen yang melayang di balik kelopak mataku. Tanganku bergerak, jemariku menjepit tiga benda itu, lalu menyambitnya ke tengah-tengah jidat pemuda berparas elok yang menjadi lawanku. Ia terbunuh dengan tiga sujen yang menancap penuh. Nyaris bersamaan dengan seranganku, aku mendengar jerit mengerika yang terputus. Seketika aku membuka mata, dan memang pemuda itu roboh terlentang dengan tiga sujen tegak berdiri di atas dahinya!
“Oh, ilmu apakah ini?” aku memekik dalam hati.

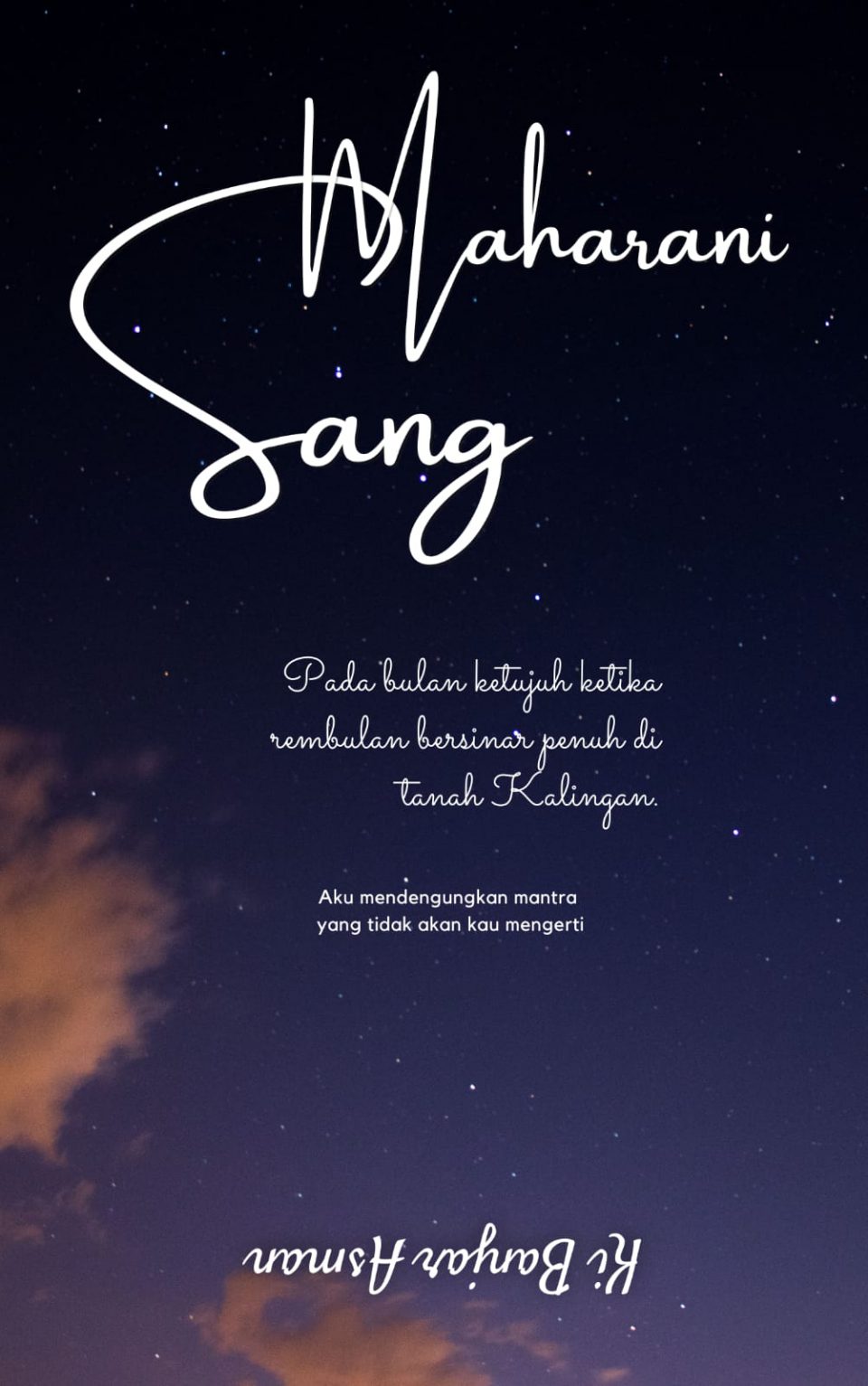
1 comment
[…] Bulan Telanjang 16 […]